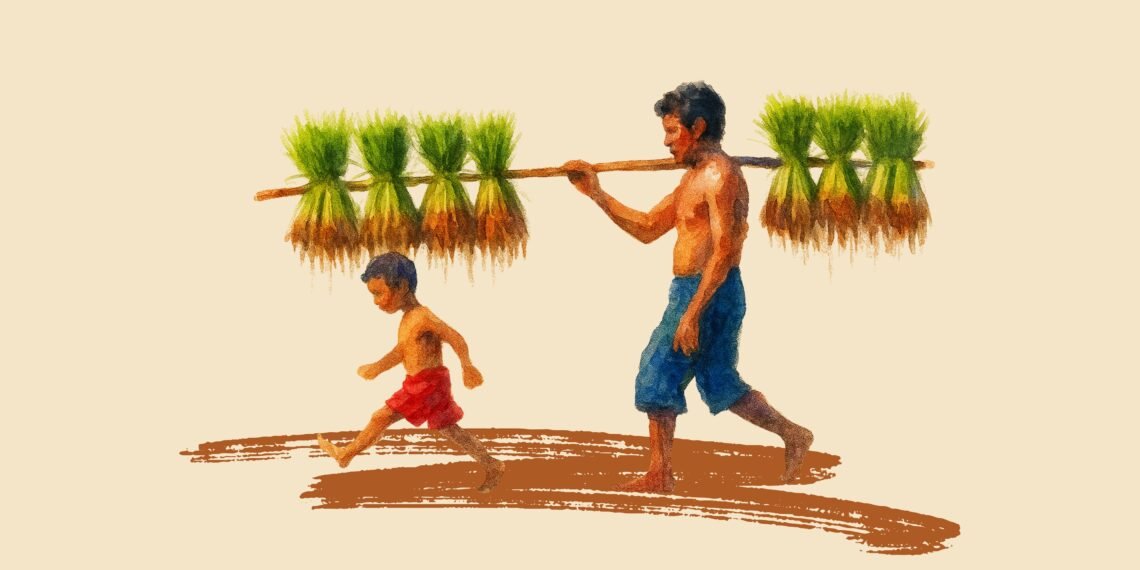DULU, desa saya tenang. Semua orang berdaya dan tak ada yang merasa tertinggal. Bapak-bapak punya acara tahlilan rutin setiap malam Jumat, tempat mereka berkumpul dan mendoakan para keluarga yang sudah meninggal dunia sambil berbagi cerita. Ibu-ibu punya manaqiban, tradisi yang bukan hanya soal doa tapi juga ruang untuk saling menguatkan. Anak-anak pun tak ketinggalan, mereka punya dhiba’an, semacam latihan seni hadrah yang sekaligus jadi ruang bermain dan belajar.
Jalan tanah memang belum diaspal, jembatan sederhana masih jadi penghubung antardusun, tapi semua orang saling mengenal, dan saling percaya. Tidak ada banyak uang, tapi ada cukup. Tidak ada kemewahan, tapi ada rasa cukup dan kebersamaan.
Bahkan, di desa kami, tidak ada orang yang kelaparan. Setiap fase kehidupan selalu dirayakan dari kelahiran, khitanan, pernikahan, hingga kematian. Tradisi yang sering dianggap bid’ah dan merepotkan itu justru menjadi bentuk jaminan sosial yang nyata. Saat seseorang menikah, tetangga bahu-membahu untuk landang. Ketika ada yang wafat, seluruh warga datang, membantu, dan sebagai imbalannya, mereka pulang membawa berkat. Ini adalah bentuk solidaritas yang tak tertulis, namun dijalankan secara konsisten. Sesuatu yang bahkan di kota besar, dengan segala sistem canggih dan teknologi, belum tentu bisa dijalankan sebaik itu.
Kepala desa adalah seseorang yang kami anggap sebagai bagian dari kami, bukan penguasa kecil yang harus dilayani. Dulu, untuk menjadi kepala atau fungsionaris desa harus dengan sukarela, karena mereka tidak digaji dalam bentuk uang seperti sekarang. Penghasilan mereka hanyalah bengkok, sebidang sawah milik desa yang hasil panennya tidak pasti karena risiko luapan banjir Bengawan Solo bisa datang kapan saja sejak istilah climate change muncul. Menjadi pamong desa bukan tentang mencari untung, tapi tentang pengabdian.
Namun semuanya mulai berubah ketika negara datang dengan janji: Dana Desa. Negara datang ke komunitas membawa kapital, seolah membawa stempel yang disematkan di jidat setiap orang berbunyi: miskin. Dari Jakarta, mereka membawa “Gentong Babi” sebagai oleh-oleh. Desa, menurut mereka, adalah tempat yang tidak memiliki kekayaan dalam bentuk yang biasa dipahami oleh kota: uang, teknologi, atau bangunan megah.
Hal ini tidak hanya akan berdampak pada struktur pengelolaan pembangunan, tetapi juga pada dinamika politik desa. Ongkos politik untuk menjadi kepala desa meningkat drastis. Jika dulu jabatan kepala desa bersifat sukarela dan berbasis pengabdian, kini calon kepala desa harus mengeluarkan dana besar untuk kampanye.
Bahkan, praktik politik uang mulai marak. Demi merebut suara, sejumlah kandidat tidak segan menyuap warga dengan iming-iming bantuan langsung atau proyek pribadi kepada para “bohir”. Pemilihan kepala desa berubah menjadi ajang pertarungan modal, bukan lagi seleksi keteladanan. Ketika tertangkap pun, koruptor desa ini tak malu mengakui bahwa telah membayar hakim agar dia bebas dan membayar wartawan agar beritanya tidak dimuat di media sosial.
Sejak kebijakan ini dijalankan, data menunjukkan bahwa justru ketimpangan di desa tidak serta-merta membaik. Menurut data Badan Pusat Statistik, rasio gini di wilayah pedesaan justru menunjukkan tren stagnan dan bahkan memburuk di beberapa tahun terakhir, menandakan bahwa distribusi manfaat dari Dana Desa belum merata.
Sementara beberapa orang menikmati proyek dan akses anggaran, banyak warga lainnya tetap tertinggal atau bahkan makin terpinggirkan. Sejak tahun 2015, pemerintah menggulirkan kebijakan desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Desa yang ditransfer langsung dari APBN ke setiap desa di Indonesia. Tujuan pemerintah mulia: membangun dari pinggiran, mempercepat pemerataan, dan memperkuat otonomi desa.
Awalnya, kami menyambut dengan harap. Jalan desa bisa diaspal, irigasi bisa diperbaiki, kegiatan ekonomi bisa tumbuh. Tapi kenyataan tidak sesederhana niat. Ketika uang masuk, datang pula yang lainnya: kekuasaan, intrik, dan perlombaan pengaruh.
Dana Desa yang mestinya untuk semua, perlahan jadi milik segelintir. Kepala desa bukan lagi tetangga yang bersahaja, tapi pemilik kuasa anggaran. Rapat-rapat desa berubah menjadi formalitas. Usulan dari warga seringkali dianggap angin lalu.
Transparansi yang dijanjikan hanya sebatas spanduk dan baliho yang dipasang saat proyek dimulai, tapi tak pernah ada laporan yang benar-benar bisa dibaca dan dipahami warga.
Saya melihat sendiri, bagaimana proyek pembangunan yang seharusnya selesai dalam dua bulan molor berbulan-bulan. Jalan yang dibangun cepat rusak karena material murahan. Pekerja yang seharusnya berasal dari warga desa malah didatangkan dari luar.
Ketika kami bertanya, kami dianggap mencurigai. Ketika kami mengkritik, kami dianggap mengganggu. Seolah desa bukan lagi milik bersama, tapi sudah diambil alih oleh negara melalui birokrasi yang menjelma dalam tubuh pemerintahan desa itu sendiri. Dampak sosialnya juga nyata, bayangkan saja bahwa spektrum Politik di Pilkades ini sampai berpengaruh ke kehidupan Pribadi, barangsiapa orang yang pro ke kandidat yang kalah, akses bantuan apapun padanya bisa tertutup. Sounds familiar, right? Kini, desa saya sudah seperti miniatur Republik, pejabatnya terang-terangan mendzalimi rakyatnya dengan sengaja, tanpa tedeng aling-aling.
Namun, desa saya ternyata bukan yang pertama menjadi “korban” negara. Jauh sebelum Dana Desa, di Jambi, negara memberikan rumah-rumah bagi Suku Anak Dalam yang hidup sehari-hari hidup secara nomaden. Setiap mendengar cara hidup subsisten mereka, saya selalu teringat quotes terkenal dari Mbah Tedjo yang bilang “Orang yang menghina Tuhan adalah mereka yang takut tidak bisa makan esok hari”. Lalu, bisa ditebak bukan hasilnya setelah Negara memberikan rumah-rumah itu? Ya, rumah-rumah bantuan itu dibiarkan terbengkalai. Bahkan, atap rumah dijual dan dinding kayunya dijadikan kayu bakar. Padahal proyek ini tidak hanya memberikan rumah, tapi juga sebidang kebun, jatah makanan, dan uang tunai selama satu-dua tahun pertama. Namun semua itu tidak cukup menjamin keberhasilan.
Di sebuah desa di Papua juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Sebuah Desa pernah mendapatkan proyek “penyepatuan” untuk siswa dan masyarakat. Padahal, tanpa alas kaki saja, kaki-kaki perkasa mereka itu sanggup melintasi hutan dengan duri tanpa ragu, demi memangkur sagu. Konon, setelah empat tahun memakai sepatu, sepatu-sepatu itu rusak dan tak layak pakai lagi. Yang tragis, telapak kaki mereka yang dulu kuat, kini menjadi lunak dan tak tahan berjalan di tanah Papua tanpa alas. Hasilnya, mereka justru kesakitan.
Bukankah ini justru membuat mereka tergantung dan lebih miskin dari sebelumnya?
Lalu, apakah mereka pernah introspeksi diri mengapa proyek-proyek seperti ini sering gagal? Ya enggak, ini karena si pembawa program gagal memahami cara hidup masyarakat setempat. Lebih tragis lagi, setelah proyeknya gagal, yang disalahkan justru komunitasnya. Mereka dianggap boros, malas, atau tidak bisa menabung. Padahal, kalau saja ada kemauan untuk bertanya dan memahami lebih dulu, mereka akan tahu bahwa contoh cara hidup yang dijalani oleh orang-orang “miskin” ini yang justru sangat logis dan berkelanjutan dalam konteks kepercayaan dan hubungan mereka dengan alam. Mereka percaya bahwa rezeki diberikan setiap hari oleh Tuhan, dan alam akan menyediakan semua yang dibutuhkan jika dirawat dengan baik.
Proyek pemiskinan secara kultural ini kerap datang dalam rupa proyek yang tampak mulia: bantuan, konservasi, pendidikan, misi kemanusiaan, atau pengenalan sistem ekonomi uang melalui pasar. Sayangnya, semua itu sering tidak disesuaikan dengan konteks budaya setempat. Akibatnya, nilai-nilai lokal yang sudah mengakar tergantikan oleh sistem luar yang belum tentu lebih baik. Ini adalah jenis kerugian yang tak ternilai dan sering kali irreversible. Kesenian yang punah, bahasa yang hilang, hingga cara hidup yang perlahan terkikis, adalah sebagian dari kehilangan yang tidak dicatat dalam laporan pembangunan. Sering kali, negara hadir ke desa bukan hanya dengan membawa program, tapi juga membawa cara pandang. Tidak jarang, pendekatan pembangunan dilakukan dengan memberi label-label yang tidak berasal dari warga sendiri.
Oleh karena itu, seharusnya negara sadar bahwa pada setiap kebijakan, negara harus sadar bahwa tidak semua sudut pandang dari luar bisa dipaksakan begitu saja di desa. Negara harus sadar bahwa tidak semua cara pandang pembangunan dari kota atau pusat bisa serta-merta cocok diterapkan di komunitas lokal.
Padahal, desa menyimpan kekayaan yang jauh lebih beragam: alam yang lestari, budaya yang hidup, solidaritas sosial yang kuat. Satu hal yang sering dilupakan adalah, standard kebahagiaan yang diukur dari jumlah uang sebagaimana dibawa negara lewat berbagai program bantuan tidak selalu relevan di desa. Banyak warga yang dalam statistik dikategorikan sebagai miskin, justru menjalani hidup dengan bahagia dalam kesederhanaan.
Mereka tidak bergantung pada penghasilan bulanan atau rekening bank, tapi pada kekuatan jaringan sosial dan rasa saling memiliki. Desa adalah contoh terbaik bahwa apa yang ditanam, itulah yang dituai. Warga desa terbiasa melakukan kebaikan dan gotong royong bukan karena mengharapkan imbalan, melainkan karena itu bagian dari keseharian. Kebaikan yang dilakukan secara konsisten itu mereka tuai setiap hari dalam bentuk kedamaian, saling bantu, dan rasa aman yang sulit ditemukan di tempat lain. Kebahagiaan mereka tidak lahir dari konsumsi barang mewah, melainkan dari kehidupan yang selaras dengan alam dan komunitas. Maka, ketika negara datang membawa standar kebahagiaan versi kota, sering kali itu justru mengacaukan keseimbangan yang sudah terjaga. Kemungkinan besar, kita yang di kota tidak bisa melihatnya karena justru tidak memiliki itu semua.
Setiap desa punya ritme sosial, budaya, dan sejarahnya sendiri. Apa yang dianggap solusi dari luar, bisa jadi malah memecah harmoni yang sudah lebih dulu hidup dan terjaga di dalam. Maka pendekatan pembangunan semestinya dilakukan dengan kerendahan hati, bukan dengan mental membawa jawaban.
Kita mungkin merasa bahwa pendekatan kita sebagai orang kota, orang terpelajar, orang yang merasa punya solusi adalah sesuatu yang keren dan canggih. Tapi di desa, itu belum tentu berarti apa-apa. Kearifan lokal, nilai-nilai hidup bersama, dan kemampuan desa dalam merawat dirinya sendiri sering kali jauh lebih kuat daripada intervensi luar yang berbekal teori dan proposal.
Maka alih-alih menggurui, kita perlu mendengarkan. Alih-alih menawarkan formula instan, kita perlu belajar menghargai cara hidup yang sudah lama berjalan dan terbukti menjaga harmoni. Sebab desa bukan ruang kosong yang perlu diisi, melainkan ruang hidup yang perlu dihargai.
Indikator seperti GDP sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan, namun sesungguhnya sangat terbatas. GDP hanya menghitung pendapatan finansial per kepala dalam satu tahun, tanpa pernah dikaitkan apalagi dikurangi dengan hilangnya keanekaragaman hayati, punahnya bahasa lokal, atau lenyapnya kekayaan budaya seperti tarian, benda seni, obat tradisional, cerita rakyat, dan mantra. Modal sosial kepercayaan, gotong royong, kepedulian antarwarga tidak pernah divalidasi dalam angka. Padahal, jumlahnya tak ternilai dan tak tergantikan. Maka, apa gunanya GDP naik dua kali lipat jika semua yang kita punya sebagai bangsa justru hilang tak bersisa?
Ini disebut bantuan, tapi sebetulnya adalah bentuk pemiskinan. Sama halnya dengan cerita tentang penggantian minyak babi tradisional dengan sabun oleh para pendatang di Papua. Akibatnya, angka kematian akibat malaria justru meningkat. Minyak babi yang dianggap kotor dan bau oleh orang luar, ternyata punya fungsi yang sangat penting. Padahal penggunaannya tidak pernah melanggar hak siapa pun.
Kami tidak ingin kembali ke masa lalu yang serba kekurangan. Tapi kami juga tidak ingin masa kini yang penuh manipulasi. Kami ingin desa kami kembali dengan kebersamaan, dengan semangat gotong royong, dengan pemimpin yang benar-benar hadir untuk rakyatnya, bukan untuk proyeknya.
Negara boleh memberi, tapi jangan sampai mengambil yang paling berharga dari kami: rasa memiliki desa kami sendiri. Jika ingin benar-benar membangun desa, mulailah dari menghormati bahwa setiap desa unik dengan kultur, adat, dan cara berdaya sendiri-sendiri. Orang-orang yang datang ke desa seharusnya tidak membawa banyak bicara, melainkan membawa banyak telinga. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tanpa prasangka dan tanpa niat untuk mendikte.
Pada akhirnya, yang paling tahu kebutuhan desa adalah orang desa itu sendiri. Negara tak bisa serta-merta menyeragamkan atau mengatur semuanya dari atas, tanpa mendengarkan cara hidup yang telah terbukti menjaga keseimbangan selama bertahun-tahun. Negara seharusnya hadir untuk menghormati yang lokal, bukan menggantinya. Dapat mendengar lebih banyak, dan bicara lebih sedikit.