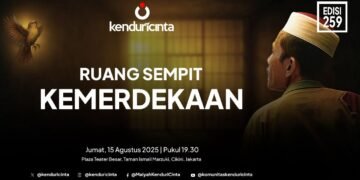Dalam surat Az-Zariyat ayat 49, Allah berfirman: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”
Prinsip berpasang-pasangan ini mewujud dalam segala hal yang lazim kita kenal, misalnya makhluk–Khaliq, pria–wanita, baik–buruk, bumi–langit, surga–neraka, jauh–dekat, sedih–bahagia, kuat–lemah, menang–kalah, benci–cinta, bodoh–pintar, hilang–ketemu, pergi-datang, tinggi–pendek, hingga siang–malam, timur–barat, matahari–rembulan, dan seterusnya.
Jika kita elaborasi lebih jauh, pasangan itu bisa bersifat koheren, komplementer, kausal, inkoheren, atau bahkan konfrontasional. Dalam khazanah sastra, misalnya, termanifestasi menjadi ungkapan “bagai pinang dibelah dua”, “siapa menanam akan menuai”, “buah tidak jatuh jauh dari pohonnya”, atau “satu-satunya hal yang tak pernah berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri”, dan sebagainya.
Dari sini, pernahkah kita sedikit usil bertanya? Kalau segala sesuatu diciptakan berpasangan, lalu pasangan dari cahaya itu apa? Sebab, kalau gelap–terang itu dampak logis saja dari hadir atau tidaknya cahaya.
Jika kita mendefinisikan cahaya secara ilmiah sebagai dualitas gelombang–partikel—hasil eksitasi elektromagnetik yang memancar tanpa memerlukan medium—apakah kita sudah serius menjadikan sifat ini sebagai petunjuk untuk menjawab pertanyaan tentang karakter ‘kejombloan’ cahaya?
Atau, setidaknya, kita jadikan acuan awal untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang makna Tauhid melalui apa yang Tuhan maksud dengan Nūrun ‘alā Nūr atau “cahaya di atas cahaya”, yang metaforanya dibagi lagi menjadi misykat, zujajah, (laksana) kaukab, dan misbah? Lalu apa pula maksud dan makna adanya Nur Muhammad yang oleh para sufi disebut sebagai “cahaya awal yang diciptakan Allah” sebelum segala sesuatu, yang kemudian bermanifestasi menjadi Rasulullah Muhammad SAW?
Dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 35 dijelaskan:
“Allah (Pemberi) cahaya (pada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya seperti sebuah lubang (pada dinding) yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang (yang berkilauan seperti) mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat; yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). Allah memberi petunjuk menuju cahaya-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
Dari aspek apa pun, misteri tentang cahaya masih banyak sekali yang belum terungkap. Meskipun faktanya, metafora cahaya sudah begitu kuatnya mewarnai perjalanan peradaban hidup manusia. Ide tentang era pencerahan yang menggunakan terminologi Enlightenment yang dimulai sejak akhir abad ke-17 di Eropa, misalnya, hingga urusan remeh-temeh pembaruan status di media sosial, atau sesederhana menyalakan lampu teplok di pelosok desa di lereng Gunung Merbabu, tak sejengkal ruang dan waktu pun yang kita lewati tanpa media perantara yang kita kenal dengan cahaya.
Kenduri Cinta edisi bulan Oktober ini kita fokuskan untuk belajar lagi, lebih meluas dan mendalam, seraya bertafakur kembali dengan lebih khusyuk dan rendah hati untuk memahami keberadaan kita—sebagai individu, keluarga, atau entitas yang lebih luas sebagai komunitas kecil hingga sebagai bangsa—dengan menghadirkan lagi energi misterius yang kita sebut sebagai cahaya.
Membincang cahaya dari Surah An-Nur ayat 35 di atas, kita juga tentu ingat pemikiran Al-Ghazali tentang lima tingkatan ruh untuk memetakan bagaimana cahaya Ilahi ditangkap: indra sebagai dinding berlubang yang menerima sinar; khayal sebagai zujajah yang menyimpan dan memantulkan; akal sebagai mishbah yang mengolah dan menimbang; pohon zaitun sebagai sintesis ilmu yang melampaui satu disiplin; lalu pendar zaitun tanpa sentuh api sebagai ruh kenabian yang memberi arah pamungkas.
Secara analogis dan filosofis, hidup kerap diibaratkan malam yang mengkondisikan kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kegelapan bukan entitas tandingan terang, melainkan ketiadaan cahaya yang memantik pencarian. Seseorang menjadi cahaya ketika bermanfaat bagi sesama—kadang bukan materi, melainkan hadir dan mendengarkan hingga hati orang lain merasa lega. Khoirunnas anfa‘uhum linnas menjadi penanda sederhana: manfaat adalah cahaya.
Di Maiyah, penyelaman ilmu dan penyerapan hikmah tentang cahaya sudah sangat banyak. Kita bisa runut misalnya dari salah satu puisi Cak Nun Tahun 1988 yang berjudul Tahajjud Cintaku, salah satu baitnya, mencoba menafsirkan cahaya sebagai berikut:
Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima Kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara Katakan kepadaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka Sedang bagi keadilan hukum ia menyediakan dirinya Ke mana pun memandang yang tampak ialah kebenaran Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang
Atau simaklah bait awal dan akhir dari lirik lagu kolaboratif Cak Nun bersama almarhum Franky Sahilatua berjudul Padhangmbulan di album Perahu Retak yang dirilis tahun 1996 berikut:
Cahaya kasih sayang menaburi malam Hidayah dan rembulan menghadirkan Tuhan Alam raya, cakrawala pasrah dan sembahyang Yang palsu ditanggalkan yang sejati datang Yang dusta dikuakkan, topeng-topeng hilang Jiwa sujud, hati tunduk pada-Mu, Tuhanku … Sesudah senja di ujung duka Nikmatilah mengalirnya cahaya
Sabrang, penerus generasi “pengangon” Maiyah, juga banyak menorehkan pesan-pesan penting untuk menghadirkan cahaya. Metafora ‘Sebelum Cahaya’ di salah satu judul lagu Letto pada album Don’t Make Me Sad tahun 2007 misalnya, mengajak dan memberi ruang luas kepada kita untuk mentadaburi maknanya sehingga bisa dipakai oleh siapa saja, kapan saja, tentang apa saja, dan di mana saja. Bersama Cak Nun, Sutradara Viva Westi, dan insan sineas Indonesia yang hidupnya bergelut dengan sorot cahaya dan layar putih, tahun 2012 Sabrang juga sempat memproduksi film berjudul Rayya: Cahaya di Atas Cahaya.
Sabrang juga tekun menelusuri keajaiban pendaran cahaya secara ilmiah berbasis teorema matematis, prinsip-prinsip fisika, dan aplikasi empiris berbasis komputasi, beserta semua manifestasi sosial, politik, dan kulturalnya. Simaklah lirik-lirik lagunya yang nuansanya tak jauh dari pendaran cahaya. Bahkan judul lagu terakhirnya, Sebening Senja, adalah pantulan dari kecenderungan imajinasi naluriah dan insting musikalitasnya yang selalu menghadirkan spektrum cahaya.
Jangan lupa, Surah An-Nur ayat 35 juga menisbatkan cahaya tersebut pada sebuah material luminescence berupa minyak dari sebuah pohon zaitun yang diberkahi, yang tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat.
Pada ranah fisika, kimia, dan biologi, lazim diperdebatkan: lho, apa hubungannya foton dengan pohon? Jawabannya, ada. Di pohonlah sintesis dengan mendayagunakan foton—alias cahaya berwujud—terjadi. Alias, fotosintesis. Mekanisme biokimia ini terjadi pada tumbuhan yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa (gula) dengan menggunakan karbon dioksida dan air, menghasilkan oksigen sebagai produk sampingnya.
Kalau pohon dan tanaman saja bisa, dengan amtsal dan prinsip dasar hidup yang sama, seharusnya kita sebagai manusia bisa jauh lebih advance mengelola energi untuk kemaslahatan alam semesta. Amanah sebagai khalifah yang dikaruniai akal dan intelektual yang luar biasa telah terbukti membuat manusia mampu mengubah dan mengolah apa pun dari dunia ini menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat—dengan anugerah Cahaya-Nya.
Ada juga fenomena unik pada tanaman yang disebut dengan etiolasi, yaitu merujuk pada proses pertumbuhan yang cepat di tempat gelap tanpa cahaya, namun ditandai dengan batang yang memanjang tidak kokoh, daun yang pucat, serta ruas yang lebih panjang. Perilaku mereka adalah cermin dari hidup manusia yang mengisolasi dirinya dalam sebuah kriteria eksklusif semu berbasis klaim “paling” namun nir manfaat bagi kehidupan kolektif—alias lawan dari manfaat, yakni mudarat.
Pada arena kultural, bukankah tradisi pementasan wayang kulit juga sejatinya sebuah pendekatan atau metodologi berbasis pantulan cahaya (agar tercipta bayangan—wayang, “bayang”—pada layar) sebagai refleksi (lagi-lagi pantulan) untuk menilai diri kita sendiri: seperti apa, seperti siapa, dan konsekuensi logis apa yang harus kita hadapi dari setiap pilihan perilaku hidup yang kita jalani?
Jika semua amtsal cahaya—berbasis kitab suci hingga pemahaman terhadapnya yang dipendarkan melalui bangku-bangku sekolah dan universitas, bahkan dihadirkan dalam naskah-naskah drama, novel, dan film—telah hadir berpuluh tahun, namun yang kemudian viral adalah fenomena “Indonesia Gelap”, ditambah respon elite politiknya yang justru konfontatif: “Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia!”, maka tampaknya, sebagai bangsa, kita perlu duduk bersama lagi, belajar menghadirkan cahaya bersama-sama.
Saking pentingnya, kita bahkan sama sekali dalam kegelapan untuk memahami semua fenomena yang terjadi akhir-akhir ini.
Demo massal yang berakhir dengan penjarahan—yang justru membiaskan aspirasi asli ke trivia remeh-temeh yang tidak relevan—reshuffle kabinet, berbagai bias dalam dialektika historis Israel–Palestina, panggung musiman bernama “Sidang Umum PBB” yang ngos-ngosan mencoba memelihara keamanan dan perdamaian internasional tanpa pernah mampu menghukum si biang keonaran, dan lain sebagainya, itu semua membuktikan kita sama sekali belum memiliki kemampuan menghadirkan cahaya kebenaran untuk mensintesis semua yang ada dari anugerah-Nya guna ditransformasikan menjadi suatu energi besar yang diberkahi.
Boro-boro untuk penghadiran manfaat; lha wong untuk pengakhiran mudarat saja masih jauh panggang dari api. Jangankan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi, mengurangi sedikit saja beban penderitaan mereka dengan amanah juga belum mampu kok.
Apakah jangan-jangan justru di situ inti persoalannya? Semua ini berlarut karena mental model dan orientasi peradaban kita masih terkungkung pada obsesi tentang api, jelaga, emisi karbon, dan segala fatamorgana rinciannya? bukan pada An-Nur sejati yang diteladankan oleh Nur Muhammad!
Karena Cahaya-Nya ternyata punya karakteristik adikodrati yang unik, yakni ia Berpendar (meskipun) tidak tersentuh api (An-Nur:35). Pendar. Bukan sekadar nyala. Pendar tidak meninggalkan jelaga hitam yang terkadang sedikit mengganggu jika singgah di kening paras jelita sang kekasih.
Cahaya semisal itu yang perlu kita hadirkan.
Meskipun membutuhkan uraian panjang, sepanjang karakter cahaya, cahaya pada akhirnya tidak berhenti pada definisi. Ia mengalir sekaligus menjadi manifestasi melalui cara sekaligus perilaku kita menimbang, cara kita hadir, dan cara kita merawat yang rapuh. Di antara siang dan malam, antara ilmu dan laku, antara individu dan kelembagaan, An-Nur bergerak seperti aliran darah, berhembus seperti nafas—tenang namun terukur, dan cukup untuk menunjukkan arah kepada kesejatian hidup.
Maka, bila malam masih panjang, cahaya bukan semata kabar tentang kegelapan. Ia juga kabar tentang kesediaan memelihara minyak, mengelap kaca yang bernoda, dan menjaga pelita dari angin yang tergesa. Ketika fajar tiba, ia yang lahir bukan hanya milik satu rumah, melainkan merambat pelan ke gang-gang, kolong-kolong, dan lobang-lobang sempit yang telah lama menanti terang.