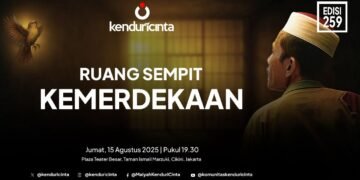“What’s in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet.” — William Shakespeare, Romeo and Juliet (1590)
Kalimat ini menjadi quote abadi yang melintasi zaman dan budaya. Ada benarnya memang, nama bunga mawar tak akan mengubah baunya. Esensi suatu hal tidak bergantung pada label atau sebutannya. Wangi khas mawar tak berubah meskipun namanya diganti menjadi kenikir. Namun, dalam khazanah Islam yang juga selaras dengan beragam tradisi spiritual Nusantara, nama bukan sekadar penanda. Ia adalah doa, aspirasi moral, harapan orang tua atau sang pemberi nama, bahkan menjadi semacam penyimpan memori kognitif yang melekat seumur hidup. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban, Nabi Muhammad bersabda, “Baguskan namamu, karena dengan nama itu kamu akan dipanggil pada hari kiamat,” menegaskan bahwa nama membawa tanggung jawab ontologis.
Pentingnya penamaan bahkan bisa ditelusuri hingga narasi awal penciptaan manusia pertama, Nabi Adam. Di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, “Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkannya kepada para malaikat.” Peristiwa ini juga menegaskan betapa fundamentalnya penamaan dalam peradaban manusia. Namun, seperti sering terjadi, ayat ini kerap diterima secara taken for granted, jarang ada yang mencoba menemukan pesan-pesan yang tersirat di baliknya. Apa sebenarnya yang diajarkan Tuhan kepada Adam?
Dalam dialektika Maiyah, Cak Nun pernah mengajukan pertanyaan sejenis yang menggelitik: kalau yang Tuhan ajarkan ke Nabi Adam adalah nama-nama benda—seperti “pohon”, “air”, atau “manusia”, bukankah penamaan adalah produk budaya yang lahir dari konsensus kolektif, interaksi sosial, dan proses kognitif manusia? Mengapa harus diajarkan langsung oleh Tuhan? Pertanyaan ini membuka celah pembelajaran, riset lintas ilmu, dan refleksi. Jawaban yang paling benar tentu hanya diketahui oleh-Nya, dan ini bukan sesuatu yang akan kita diskusikan.
Namun setidaknya, jawaban dialektisnya bisa kita arahkan pada gagasan bahwa yang diajarkan oleh Tuhan kepada Nabi Adam adalah prinsip kognitif universal—semacam algoritma kesadaran yang memungkinkan manusia mengenali realitas, membedakan esensi, dan membentuk makna kolektif. Bukan sekadar diberitahu “ini daun”, “ini batu”, “ini kayu”… apalagi seremeh-temeh menyebutkan nama-nama ikan untuk mendapatkan hadiah sepeda.
Penamaan, dalam pengertian ini, merujuk pada kemampuan mengidentifikasi dan mengkonstruksi sesuatu secara konseptual, bahkan simbolik, adalah fondasi bagi pemahaman, intelektualitas, moralitas, dan tanggung jawab. Di dalam bahasa Jawa, penamaan manungso (manusia), misalnya, tidak sekedar nama yang membedakan dengan kewan lan wit-witan (hewan dan tumbuhan), namun secara filosofis diambil dari kesadaran manunggaling roso**—bersatunya rasa. Pola penamaan semacam ini juga bukan sekedar kreativitas linguistik, tetapi sebuah petunjuk ketajaman eksplorasi budaya yang memandang manusia bukan sebagai predator bagi sesamanya (Homo homini lupus), melainkan sebagai makhluk yang dibangun dari kedalaman empati dan keluasan kesadaran.
Dengan demikian, pemberian “nama” kepada segala sesuatu yang diajarkan kepada Nabi Adam bisa jadi sebuah metafora pembuka jalan menuju kesadaran diri yang paling fundamental. Nabi Adam diajarkan bahwa dirinya adalah bagian dari tatanan kosmis yang utuh—mikrokosmos yang memantulkan makrokosmos—sekaligus khalifah di muka bumi. Namun, manusia dalam kodratnya adalah makhluk yang mudah lupa. Kata insan sendiri dalam bahasa Arab berakar dari nasiya (lupa), sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab: Al-insānu maḥallus syahwi wan nisyān—manusia adalah tempat nafsu dan lupa.
Lupanya manusia sering kali menyentuh hal-hal mendasar. Manusia lupa dari mana asalnya: dari segumpal tanah, menjadi nutfah, lalu segumpal darah dan daging yang ditiupkan ruh. Ia lupa bahwa keragaman suku dan bangsa diciptakan bukan untuk saling membanggakan diri atau bermusuhan, melainkan agar saling mengenal. Ia lupa bahwa tujuan utama penciptaannya adalah ibadah—dalam makna luas sebagai keterhubungan dengan Yang Maha Ada. Ia lupa betapa istimewanya bentuk penciptaannya dibanding makhluk lain, yang menjadikannya layak menyandang amanah kekhalifahan.
Kesadaran yang utuh, yang mengingat semua ini, tidak datang dengan sendirinya. Dalam bahasa Inggris dan tradisi akademis Barat, “kesadaran” terurai menjadi tiga lapis: consciousness, yaitu keterjagaan fisik; awareness, yaitu kewaspadaan terhadap lingkungan dan diri sendiri; serta conscience, yaitu hati nurani yang menimbang baik dan buruk. Seseorang bisa memiliki dua lapis pertama—sebagai ilmuwan jenius, pemimpin karismatik, atau eksekutif cakap—namun kehilangan lapis ketiga. Di situlah muncul fenomena elit yang rasional namun korup: sadar secara kognitif, tapi buta secara moral.
Inilah yang menunjukkan bahwa kesadaran bukan warisan, melainkan perjalanan terus-menerus. Dalam idiom Jawa dikenal dengan eling lan waspodo (ingat dan waspada). Ia bersifat subjektif, rentan terfragmentasi, dan harus dibangun secara aktif sepanjang hidup. Ia on-off mengikuti dinamika perjalanan kemanusiaan. Ia tumbuh perlahan dari kepingan-kepingan memori masa lalu dan harapan masa depan serta dari potongan-potongan pengalaman yang silih berganti. Ia mengadopsi dan beradaptasi dengan ajaran agama, nilai-nilai budaya, ideologi politik, norma-norma sosial, hingga dialog yang jujur, refleksi atas kesalahan, trauma, kegembiraan yang menyatukan, bahkan dari momen-momen kecil yang lucu dan absurd. Dari serpihan-serpihan itulah, manusia perlahan belajar kembali utuh dengan seluruh mozaik ingatannya.
Konsep Fragmen Kesadaran menjadi relevan di sini. Seperti puzzle tanpa gambar panduan, setiap keping datang dari sumber yang berbeda: ayat suci, hasil riset sains, cerita nenek, percakapan insidental, fatwa ulama, nasihat motivator, status atau caption di media sosial, atau keheningan di tengah hujan. Proses ini tidak menjamin pencapaian kebenaran absolut—yang hanya milik Tuhan—tetapi membawa kita mendekatinya dengan integritas, kerendahan hati, dan keterbukaan. Kesadaran, dalam pengertian ini, bukan tujuan, melainkan perjalanan menuju eling—mengingat kembali asal-usul dan *waspodo—*untuk senantiasa berada pada jalur tujuan eksistensi. Perjalanan ini melibatkan dua gerak sekaligus: menjadi Abdullah (hamba yang menerima, yang peka terhadap wahyu dan realitas), dan Khalifatullah (pengelola yang bertindak, yang mengelola dunia dengan tanggung jawab). Tanpa keseimbangan antara menerima dan bertindak, manusia mudah terjatuh ke arah fanatisme dogmatis atau aktivisme tanpa akar nilai.
Di tengah arus informasi yang penuh manipulasi, friksi sosial, dan senjata sihir bernama hoaks, sadar diri, mawas diri, dan introspeksi diri menjadi benteng terakhir. Memperkuat pertahanan ini memerlukan lebih dari sekadar data; ia membutuhkan literasi nilai: kemampuan melihat root cause, dan melestarikan tindakan yang terkontrol oleh kebijaksanaan.
Di sinilah ruang seperti Maiyah hadir bukan sebagai partai, ormas, atau komunitas bisnis, melainkan sebagai forum kesadaran nilai—ruang di mana manusia belajar dengan tekun untuk mengenal dirinya sendiri, karena, seperti hadist qudsi yang terkenal, “Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya.” Pembelajaran di Maiyah tidak dimulai saat acara dimulai, tetapi setelahnya—ketika nilai itu dihidupkan dalam kesadaran dan tindakan sehari-hari secara istiqomah.
Jika lupa dan lalai adalah kodrat manusia, maka satu-satunya jalan pulang adalah terus mengumpulkan fragmen kesadaran dengan rendah hati, kritis, dan penuh tanggung jawab. Bukan untuk mencapai kebenaran penuh, yang mustahil bagi manusia, melainkan untuk terus mendekatinya, lapis demi lapis, keping demi keping. Pertanyaannya bukan lagi “apa kebenaran itu?”, melainkan: fragmen kesadaran macam apa yang sedang kita kumpulkan hari ini dan ke arah pemahaman seperti apakah kepingan-kepingan itu sedang membawa kita?