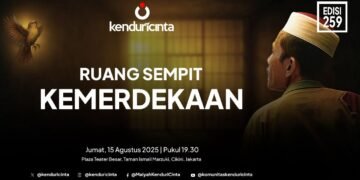Kulihat Ibu Pertiwi
Sedang bersusah hati
Air matanya berlinang
Mas intannya terkenang
Untaian Ibu Pertiwi karya Kamsidi Samsuddin—kemudian digubah oleh Ismail Marzuki yang namanya tak lekang oleh waktu dan terabadikan dengan penuh hormat sebagai lokasi gelaran Kenduri Cinta sejak seperempat abad yang lalu—rasanya cukup mewakili hati kita hari-hari ini: barisan kata-kata ini bukan sekadar syair, melainkan cermin getir kenyataan bangsa hari-hari belakangan ini.
Pasca Perayaan 80 Tahun Kemerdekaan RI dan Kenduri Cinta Agustus dengan tema “Ruang Sempit Kemerdekaan” yang meneguhkan rasa syukur seraya berintrospeksi diri, sekonyong-konyong ternyata kita diuji lagi. Harapan atas kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan empati yang tersimpan di sudut-sudut kesabaran sanubari rakyat kecil kembali pecah, tersakiti oleh ulah dan akhlak tak terpuji dari para elite negeri.
Dampaknya pun menyesakkan dada. Anak-anak belia Ibu Pertiwi yang memang sudah terhimpit kesulitan hidup sehari-hari kembali berguguran dalam perjuangan menuntut reformasi dan ditunaikannya janji-janji.
Marah, kecewa, dan sedih silih berganti mengetuk nurani segenap warga bangsa yang merasa dikhianati dan dianggap tidak mengerti. Semua memendam geram untuk menuntut keadilan dan pengungkapan kesewenang-wenangan demi satu alasan, karena kita menghormati dan mencintai Ibu Pertiwi. Pada titik inilah kita diingatkan bahwa cinta kepada Ibu Pertiwi tidak hanya berupa rasa, tetapi juga tanggung jawab untuk merawatnya.
Ketika cinta terluka—apa pun alasannya—seharusnya tidak membuat kita kalah, menyerah, atau mati begitu saja. Maulid Nabi bulan ini, sebagai momentum kelahiran tanda cinta-Nya bagi semesta, perlu kita hayati untuk membasuh luka. Lahirnya Nur Muhammad jangan berhenti pada renung; jadikan benang-jarum energi jasmani-rohani untuk menjahit dan menata kembali koyakan kekecewaan yang terlanjur pecah di sana-sini.
Manifestasi luka itu boleh jadi berwujud unjuk rasa yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Aksi-aksi sporadis yang mengisyaratkan puncak gunung es dari masalah struktural kebangsaan kita yang akut. Tak hanya krisis legitimasi dan kepercayaan (trust deficit) terhadap elite penyelenggara negara, tetapi juga krisis persepsi positif yang mewujud pada ketidakadilan fiskal yang dalam, beban ekonomi dan sosial rakyat yang terus dibiarkan, serta nirempati para petinggi atas situasi yang dihadapi.
Pada tingkat yang lebih mendasar, instrumen pajak yang merupakan kontrak sosial antara rakyat dengan pemerintah tak boleh lagi ditarik secara sembarangan, apalagi digunakan secara sembrono yang menguntungkan pihak tertentu dan memicu luka-luka kolektif lainnya. Ruang-ruang produktif yang menjadi jawaban atas beratnya beban hidup masyarakat harus menjadi perhatian utama bagi para pemegang amanah kolektif untuk memulihkan situasi.
Tindak kekerasan aparat dalam bentuk dan atas alasan apa pun yang merenggut nyawa—Affan Kurniawan dan anak bangsa yang lain—juga tak boleh lagi menjadi personifikasi negara atas rakyatnya.
Suka atau tidak suka, hal-hal ini mengingatkan kita bahwa Ibu Pertiwi memang lahir dari tradisi perlawanan yang secara genetik, politik, sosial, maupun kultural lestari sejak dahulu. Memori genetik kolektif kita sudah memiliki template perlawanan terhadap semua bentuk penjajahan, penindasan, perampokan, penganiayaan, dan perundungan, baik yang dilakukan oleh orang asing bathuk-bathuk angkoro yang serakah maupun kaki tangan mereka dari saudara sendiri yang tamak demi menguasai dan menjarah kekayaan emas, intan, dan insan yang dikandungnya.
Perlawanan ini sepuh dan otentik Nusantara. Sejarah panjang bangsa menunjukkan bahwa perlawanan ini bukan fenomena baru, berawal dari embrionya, ketika Sultan Demak Bintara menggempur Portugis di Malaka pada abad ke-16, dilanjutkan perlawanan Sultan Agung di Kerajaan Mataram abad ke-17 yang tak sudi tunduk di bawah ketiak muslihat VOC, diikuti perlawanan para raja dan sultan di berbagai daerah, berlanjut ke Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro (1825–1830) yang muak dengan ketidakadilan dan kepongahan pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
Kemudian, kaum terdidik yang merintis munculnya pergerakan nasional di awal abad ke-19 menggumpal menjadi Sumpah Pemuda 1928 dan titik kulminasinya pada Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, yang diteruskan dengan perjuangan revolusi, Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 oleh para ulama dan santrinya, meniupkan ruh baru bagi ide Persatuan Indonesia yang terinspirasi dari Sumpah Palapa Sang Patih Gadjah Mada tahun 1336.
Namun, kebebasan yang diraih dengan darah dan air mata ini tidak otomatis menghadirkan kedamaian. Ibu Pertiwi yang baru saja merdeka pun tak sempat menikmatinya dengan riang gembira. Hengkangnya kaum penjajah asing secara fisik dari bumi Ibu Pertiwi ternyata berganti dengan hadirnya penjajah baru dalam bentuk surupan pengaruh mereka dengan wajah lokal, namun memiliki algoritma yang sama: eksploitatif.
Perseteruan antar kelompok yang merenggut jutaan nyawa, perkelahian rebutan kekuasaan—pengaruh antar kelompok elite, muslihat berkedok politik kerakyatan, terbukti telah menjadi template berulang yang memicu rangkaian peristiwa 1965, 1974, 1991–1996, 1998, dan 2025. Ia merembeskan aroma busuk ala dedhemit semisal Ki Setra Gandha Mayit—yang tak tampak wujudnya, namun busuk tercium tajam aromanya—bergentayangan di Nusantara di depan hidung rakyat awam yang tak kunjung paham siapa dia.
Rentetan resistensi, pembungkaman, dan penyeragaman atas nama kamtibmas selama dua babak misterius Orde Baru yang berujung pada momentum Reformasi (yang tak tuntas) di 1998, hingga tuntutan rakyat atas lipstik keadilan dan kesejahteraan yang dipertontonkan segelintir elite dan kelompok kaya di tengah maraknya jargon efisiensi. Kenaikan pajak, gelombang PHK, dan lesunya ekonomi masyarakat bawah di medio 2025, semuanya bersimpul pada satu sekam angkara yang berulang-kali mendistorsi aspirasi murni dan tradisi khas perlawanan itu! Inilah yang membuat kita melihat pola berulang, seakan sejarah bergerak dalam lingkaran yang tak kunjung terputus. Itu semua karena surupan bayangan palsu dan jahat dari para penunggang yang terus mengikutinya.
Dalam situasi yang semakin rumit ini, pertanyaan besar pun muncul. Kita tidak akan pernah tahu persis apa sebenarnya yang sedang terjadi. Karena di dalam panggung dusta, adakah kejujuran yang tersisa? Seperti apa skenario kerusuhan dan kekacauan di awal, di antara, dan di akhir yang dikehendaki? Kelompok mana saja yang terlibat? Siapa saja aktor politik dan pemain ekonomi yang mengambil keuntungan dari rentetan peristiwa perlawanan rakyat atas kecongkakan para pemegang amanah yang mereka titipkan di pundaknya? Semuanya adalah sejuta tanya yang hanya segelintir manusia yang benar-benar memahaminya.
Satu hal yang jelas, korban-korban nyatanya lagi-lagi adalah kawula alit yang kemiskinannya bukanlah fabrikasi dan jerit deritanya bukanlah kosmetik atau konten para pemburu rente popularitas. Tentu, yang paling berduka adalah Ibu Pertiwi—namanya bahkan dibajak para penganiaya tanpa sungkan dan malu.
Situasi ini memang sulit. Pucuk pimpinan pemerintah mungkin tak mampu memberikan solusi lengkap yang adil untuk semua. Aparat hukum dan keamanan terjebak di tengah himpitan perlawanan yang mereka sendiri tak tahu siapa kawan dan siapa lawannya. Para ulama dan tokoh masyarakat tak lagi didengarkan fatwa-fatwanya. Pimpinan politik dan ormas-ormas terkemuka kebingungan sendiri karena bimbang dan takut ditinggalkan para pengikutnya. Kaum intelektual dan para aktivis yang senantiasa vokal memilih bungkam dan asyik dengan ucapan bersyarat yang sumir. Sementara kelompok kaya dan pemilik modal sibuk mengamankan kerajaan bisnis dan aset-asetnya.
Ini bukan lagi cerminan bangsa yang sejarah perjuangannya sempat diabadikan dengan tinta emas bertatahkan permata manikam iman-takwa, gotong royong, toleransi, dan tenggang rasa. Ini situasi darurat di mana semua saling tikam-menikam, yang pawang penjinaknya sudah tidak bisa lagi manusia biasa. Kondisi seperti ini pernah disindir oleh Cak Nun dengan tamparan “Jangan Cintai Ibu Pertiwi” pada pentas Musik-Puisi di Gedung Kesenian Jakarta, 3 April 2009.
Karena itu, kini saatnya kita berhenti sejenak, menundukkan hati, dan kembali ke sumber segala kekuatan. Saatnya kita merendah sedalam-dalamnya, memohon ampun dan taubatan nasuha kepada Yang Maha Kuasa atas jagat raya, termasuk bumi Ibu Pertiwi. Ini momentum untuk meneguhkan tawadhu’ kolektif, gondelan wusanane Gusti Kanjeng Nabi, mengharap syafaat dan kejernihan hati dan pikiran untuk mencontoh Jatmika Akhlaqul Karimah dan Waskita Rahasia Nubuwwah yang dibawa dari misi kerasulannya.
Ini adalah titik tolak kita ngangsu kawruh kembali pada Kanjeng Senapati ing Alaga Sayyidina Ngali bin Abi Thalib, yang terdepan dalam antikorupsi dan berjuang untuk keadilan, kesetaraan, serta transparansi kepemerintahan, namun sangat waskita dalam menentang penunggangan aspirasi kawula alit oleh para angkara elite. Ingat pertanyaan cerdas beliau sebagai seorang Ksatria Pandhita Telik Sandhi kepada massa campuran (asli dan bayaran) yang menyemut di depan dhalem Ngamirul Mukminin Khalifah Utsman ibn Affan RA pada bulan Mei–Agustus 656 M.
Pelajaran masa lalu menjaga kita dari pengulangan kesalahan. Kecerdasan itulah yang perlu dipakai untuk membaca peristiwa: Oktober 1952, Oktober 1965, Maret 1966, Januari 1974, Juli 1996, Mei 1998, periode 2014–2024, hingga Agustus 2025 dan seterusnya. Mengapa? Karena aspirasi murni rakyat alit senantiasa disalahgunakan dan ditunggangi angkara elite demi kepentingan mereka dari masa ke masa, sementara derita rakyat alit terus berputar perpetual bagai simulakra siklikal.
Di tengah kondisi yang gaduh, suara keras bukan satu-satunya tanda daya, sementara hening tidak selalu identik dengan menyerah dan berhenti melawan. Keduanya punya tempat: suara lantang menggugah, hening yang dipilih turut menjernihkan. Jamaah Maiyah diajarkan ketenangan—bukan untuk mundur atau diam, melainkan agar tak terseret hiruk-pikuk yang menipu. Air yang tenang menyimpan daya hidup. Dalam kerja dan relasi, mereka yang quietly hadir mungkin tak menonjol, namun menjaga keseimbangan—kekuatan mereka bertumpu pada kedalaman batin, bukan pada volume suara.
Sejalan dengan pilihan tenang-sadar yang menjernihkan, episode kali ini adalah ajakan: bershalawat, meneguhkan Rahman-Rahim Cinta Ibu Pertiwi kepada sesama anak bangsa, agar aspirasi dan bayangannya tak menjelma silat amarah, melainkan silaturahim sejati yang sama-sama tunduk sujud kepada kuasa Ilahi, bukan Angkara Dajjali.