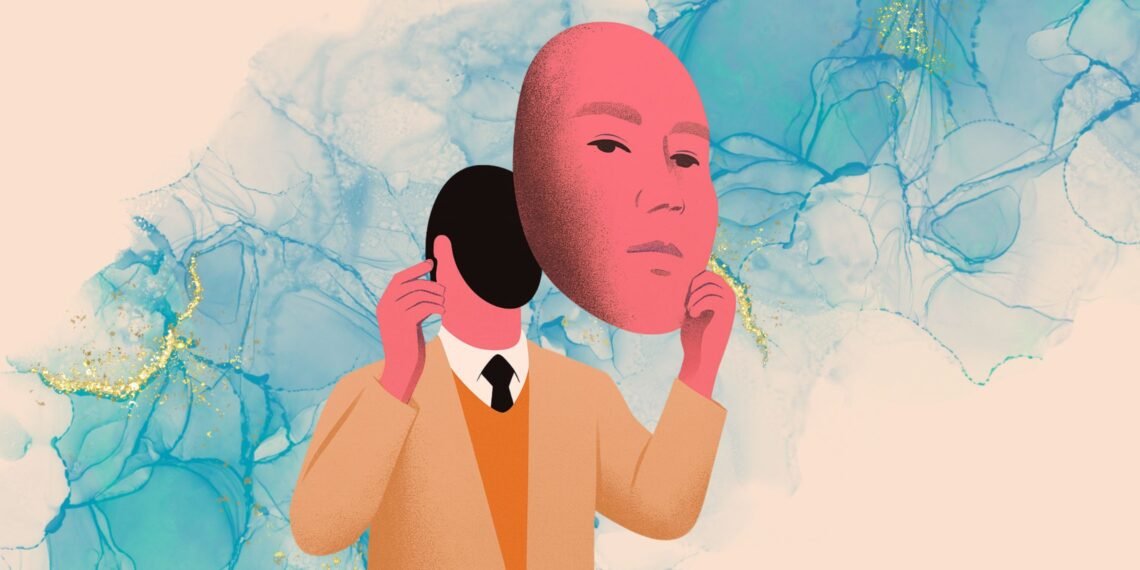SEJAK PAGI, seorang ayah sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk kedua anaknya. Ia menanak nasi, lalu menggoreng empat butir telur ceplok sebagai lauk. Tak ada tambahan apa-apa—hanya telur goreng sederhana. Di sudut rumah, sang istri tengah mencuci pakaian. Mereka berbagi peran, berbagi tanggung jawab.
Ketika waktu sarapan tiba, kedua anak duduk di meja dan mulai makan. Sang ayah memperhatikan mereka dalam diam. Saat butiran nasi berjatuhan dari piring, ia segera menegur dengan lembut—baginya, nasi adalah hasil dari keringat dan kerja keras. Setiap bulir punya makna.
Ketika anak-anak selesai makan namun masih ada sisa di piring, ia kembali menasihati. Bukan karena marah, tapi karena ia ingin anak-anaknya belajar menghargai setiap usaha—terutama yang dilakukan dengan cinta.
Ayam Mati
Ungkapan bijak dalam budaya Jawa, “Nek maem ora entek, mengko ayame mati“—yang berarti ” Jika makan tidak dihabiskan, nanti ayamnya mati”—adalah bentuk nasihat sederhana namun sarat makna. Biasanya disampaikan kepada anak-anak saat makan, ungkapan ini mengajarkan pentingnya menghargai makanan sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang diperoleh. Setiap butir nasi dianggap bernilai karena di baliknya ada kerja keras, keringat petani, dan keberkahan yang tidak boleh disia-siakan.
Namun bagi generasi sekarang, terutama yang tumbuh di lingkungan urban dan jauh dari kehidupan agraris, ungkapan ini kerap terdengar asing dan tidak relevan lagi. Dengan polos dan santai balik bertanya, “Ayamnya siapa? Kita kan nggak pelihara ayam.” Ungkapan itu pun terdengar seperti mitos yang tak masuk akal, sehingga kehilangan konteks makna aslinya. Hal seperti ini menunjukkan adanya jarak pemahaman. Padahal, inti dari pitutur tersebut bukanlah soal ayam, melainkan ajakan untuk menghargai makanan sebagai wujud syukur, serta pengingat akan pentingnya tidak menyia-nyiakan apa yang telah diperoleh.
Nasi Menangis
Di lain waktu, orang tua kembali mengingatkan dengan nada lembut yang tak pernah bosan: “Jika tidak dimakan, bahkan sebutir nasi pun akan menangis.” Sebuah ungkapan yang lagi-lagi mungkin akan dibantah oleh sebagian orang—terutama generasi yang terbiasa memaknai segala sesuatu secara harfiah. Akan bertanya, “Mana mungkin nasi bisa menangis?”
Memang sih, tidak ada hadis atau ajaran Islam yang secara eksplisit menyebut bahwa nasi akan menangis. Namun, dalam Islam terdapat tuntunan tentang adab makan yang baik: menghargai makanan, menghabiskannya, dan tidak menyisakan tanpa alasan. Semua itu bersumber dari prinsip hidup yang menekankan kesederhanaan, rasa syukur, dan upaya untuk menghindari pemborosan. Maka, meskipun disampaikan dalam bentuk simbolik atau perumpamaan, pesan orang tua tetap selaras dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agama.
Dipatuk Ayam
Kebiasaan bangun pagi bukan hanya urusan waktu, melainkan berkaitan erat dengan kedisiplinan, semangat hidup, dan kesiapan menghadapi tanggung jawab. Karenanya, orang tua kita sering mengingatkan: “Ojo tangi kawanen, rejekine ditotol ayam“—jangan bangun kesiangan, nanti rezekimu dipatuk ayam.
Petuah ini mengandung pesan penting: bahwa waktu pagi adalah momen penuh berkah dan peluang. Mereka yang memulai hari lebih awal biasanya memiliki ruang untuk berproses lebih lama, mempersiapkan diri, dan meraih hasil yang lebih baik. Sebaliknya, keterlambatan bisa membuat kita kehilangan kesempatan yang semestinya bisa didapat.
Dalam tradisi pesantren, bangun pagi bahkan menjadi budaya yang dijaga. Usai salat Subuh, para santri diajarkan untuk tidak kembali tidur. Tidur setelah Subuh dipercaya bisa mengurangi keberkahan, bahkan disebut sebagai penyebab kefakiran. Secara hukum fikih, memang tidak haram, tapi hukumnya makruh—sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan.
Ada hadis Nabi yang memperkuat nilai ini: “Seusai salat fajar (Subuh), janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki.” (HR. Thabrani)
Waktu antara Subuh hingga terbitnya matahari diyakini sebagai waktu penuh berkah dan pintu rezeki terbuka lebar. Maka, menjaga semangat pagi bukan hanya tentang produktivitas, tapi juga menyambut limpahan kebaikan yang telah disiapkan Tuhan bagi hamba-Nya yang bersungguh-sungguh.
Guru kita, Cak Nun, adalah teladan dalam hal kedisiplinan dan etos kerja yang luar biasa. Sebagai contoh, usai mengisi acara Kenduri Cinta dari pukul 20.00 hingga dini hari sekitar pukul 03.00, tak langsung beristirahat. Sesampainya di hotel, setelah membersihkan diri sebentar, langsung membuka laptop dan mulai menulis. Tak lama berselang, menuju bandara untuk mengejar flight pukul 06.00. Setibanya di Yogyakarta sekitar pukul 08.00 pagi, bukannya tidur atau beristirahat, kembali melanjutkan aktivitas menulisnya.
Kedisiplinan ini bukan hal baru. Pada era Patangpuluhan, saat tidak ada kegiatan di luar rumah, memulai pagi dengan menyelesaikan sejumlah tulisan. Setelah itu, mencuci mobilnya sendiri. Padahal, ada beberapa orang yang siap membantu dan dengan senang hati akan melakukannya.
Wewaler: Menjaga Nilai
Dari ketiga wewaler tersebut—“Ayam mati,” “Nasi menangis,” dan “Rezeki dipatuk ayam”—kita belajar bahwa petuah orang tua bukan sekadar ungkapan tradisional yang klise. Di balik kata-kata sederhana itu, tersembunyi nilai-nilai luhur tentang rasa syukur, tanggung jawab, kesederhanaan, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap rezeki.
Mungkin bahasanya tak lagi sepenuhnya dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi semangat dan ajaran yang terkandung di dalamnya tetap layak untuk diwariskan.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar berbagai wewaler atau pitutur dari orang tua—petuah bijak yang sarat makna dan nilai. Meskipun berasal dari tradisi lama, banyak di antaranya tetap relevan hingga kini. Nilai-nilai tersebut bukan hanya bagian dari warisan budaya, tetapi juga menjadi penuntun dalam membentuk budi pekerti, sikap hidup, dan kesadaran moral dalam keseharian. Tulisan ini mencoba mengangkat kembali beberapa di antaranya, sebagai pengingat sekaligus renungan di tengah perubahan zaman.