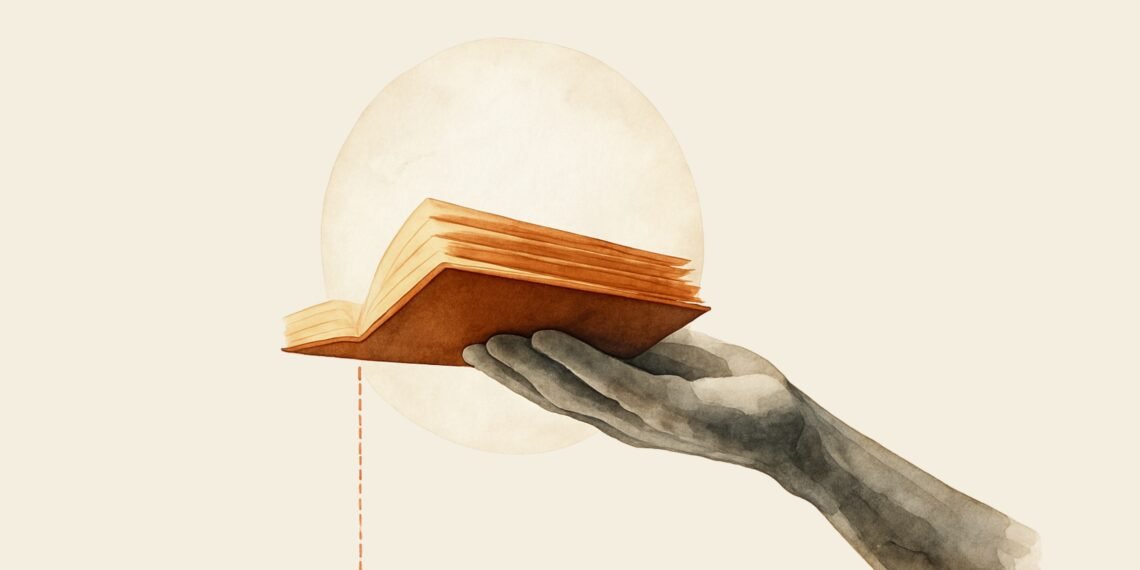MUNGKIN kita memang sedang hidup di zaman ketika sekolah lebih sering runtuh daripada tumbuh. Bukan hanya gedungnya yang ambruk setelah musim hujan, tapi juga ide dasarnya: untuk apa manusia belajar. Pendidikan kini lebih tampak sebagai urusan logistik—bantuan operasional, sertifikasi, akreditasi, dan tender proyek—ketimbang urusan kebudayaan. Ia seperti pohon yang sibuk mengurus daunnya sendiri, sementara akarnya mulai lapuk dimakan waktu dan kelalaian.
Tiap kali ada gedung sekolah ambruk, kita menyebutnya kecelakaan. Tapi mungkin itu bukan kecelakaan. Mungkin itu gejala. Runtuhnya atap adalah tanda dari rapuhnya fondasi yang lebih dalam: cara berpikir kita tentang belajar. Kita telah memisahkan “pendidikan” dari “kehidupan”, seolah keduanya dua dunia yang berbeda. Sekolah menjadi pabrik kelulusan, bukan taman pertumbuhan.
Kita membangun sistem yang tegak di atas prosedur, tapi kehilangan jiwa pembelajaran. BOS terlambat cair bukan sekadar soal birokrasi, tapi juga lambang dari mentalitas tunggu—bahwa pendidikan hanya berjalan jika uang turun dari atas. RSBI hadir dengan janji keunggulan, tapi menyisakan bau diskriminasi: pendidikan yang membedakan bahasa, bukan membebaskan manusia. Ujian Nasional, yang katanya alat ukur, berubah jadi panggung kecurangan massal; semacam ritual tahunan untuk memanipulasi kenyataan.
Guru pun tak luput. Sertifikasi lewat PLPG dirancang untuk menaikkan martabat, tapi justru menurunkan makna profesi: seolah kualitas mengajar bisa diperoleh lewat tumpukan berkas dan cap stempel. Di ruang kelas, anak-anak duduk berderet seperti statistik—angka kelulusan, nilai rapor, skor PISA—sementara dunia di luar bergerak tanpa menunggu.
Kita membutuhkan pemahaman baru tentang pendidikan, bukan sekadar revisi kurikulum. Pemahaman yang lahir dari kesadaran bahwa belajar bukan persiapan untuk hidup, melainkan bagian dari hidup itu sendiri. Pendidikan yang memberi ruang bagi anak untuk bertanya, bukan sekadar menjawab. Yang menghargai kegagalan sebagai bagian dari penemuan, bukan menakutinya dengan hukuman.
Barangkali sudah waktunya kita berhenti mencari “sekolah terbaik” dan mulai membangun “masyarakat belajar”. Sebab masa depan tidak akan datang kepada mereka yang sekadar menghafal masa lalu, tapi kepada mereka yang berani menafsirkan ulang masa kini.
Dari reruntuhan sekolah-sekolah yang ambruk itu, kita bisa memulai sesuatu yang baru—sebuah pendidikan yang tumbuh, bukan dari kebijakan yang megah, tapi dari kesadaran kecil yang jujur: bahwa belajar adalah bentuk paling manusiawi dari harapan.
Solusi pemerintah selalu datang dengan angka. Bila masalah pendidikan tampak pelik, tambahkan anggaran. Bila bangunan sekolah ambruk, bangun lagi yang lebih besar. Bila hasil belajar rendah, adakan pelatihan dan program baru. Maka pendidikan berubah menjadi hitungan persentase: 20 persen dari APBN, katanya, demi masa depan bangsa. Tapi kita tahu, yang meningkat bukan pendidikan—melainkan persekolahan.
Negeri ini tampak seperti sedang memuja sekolah, bukan belajar. Kita menganggap segala yang “berpendidikan” harus lahir dari gedung dengan papan nama resmi, dari guru bersertifikat, dari kurikulum yang dicetak oleh kementerian. Sekolah menjadi agama baru, dengan ritual harian bernama apel pagi dan doa sebelum ujian.
Padahal, mungkin di sinilah akar persoalannya. Ivan Illich, lebih dari setengah abad lalu, telah memperingatkan tentang bahaya schooling—ketika pendidikan direduksi menjadi persekolahan, dan belajar menjadi proses domestikasi. Masyarakat kemudian belajar untuk tidak belajar kecuali di bawah izin sekolah. Dalam buku Deschooling Society yang kini terasa seperti nubuat, Illich menulis bahwa sistem persekolahan justru menciptakan ketergantungan: manusia dibiasakan percaya bahwa tanpa lembaga, mereka tidak akan tahu apa-apa.
Bukankah itu yang sedang terjadi di sini? Wajib belajar berubah menjadi wajib sekolah. Belajar menjadi urusan institusi, bukan kesadaran. Anak-anak diajari menghormati guru, tapi tidak diajak menghormati pengetahuan. Mereka dipisahkan dari kehidupan nyata dengan alasan “belum cukup umur”, dilarang bekerja karena “bekerja bukan belajar”. Padahal kerja justru bisa menjadi bentuk belajar paling otentik—belajar dari kegagalan, dari tanggung jawab, dari kenyataan.
Sementara itu, masyarakat mulai kehilangan iman pada sekolah. Dari kekecewaan yang menumpuk lahirlah gerakan homeschooling, sebuah usaha kecil untuk merebut kembali hak belajar dari tangan birokrasi. Gerakan ini sering dicurigai sebagai ancaman terhadap sistem, padahal sesungguhnya ia adalah tanda kehidupan—tanda bahwa masih ada orang tua yang percaya bahwa belajar adalah urusan cinta, bukan urusan izin.
Kita mungkin harus berani mengajukan pertanyaan yang tak nyaman: mungkinkah justru sekolah itu sendiri yang menjadi sumber persoalan pendidikan kita? Barangkali selama ini kita sibuk memperbaiki dinding lembaga yang justru menyekat manusia dari kenyataan.
Illich pernah bermimpi tentang masyarakat yang belajar tanpa sekolah—learning webs yang tumbuh dari interaksi, rasa ingin tahu, dan solidaritas. Sebuah mimpi yang mungkin tampak utopis, tapi setidaknya mengingatkan kita bahwa pendidikan sejati tidak selalu berseragam, tidak selalu berbunyi bel, dan tidak selalu duduk di bangku.
Barangkali, di tengah kebanggaan akan jumlah gedung sekolah dan laporan anggaran yang menebal, kita perlu bertanya kembali: apakah yang sedang kita bangun benar-benar pendidikan—atau hanya sistem persekolahan yang makin gemuk tapi kehilangan jiwa?
Sebab bila sekolah terus menjadi tembok antara manusia dan kehidupan, maka belajar akan mati muda, dan pengetahuan hanya akan menjadi upacara rutin yang kehilangan makna.
Kita hidup di zaman ketika sekolah menjadi agama, dan ijazah menjadi kitab sucinya. Seorang anak kini bisa menghabiskan dua dekade penuh dalam sistem persekolahan—dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi—baru kemudian dihadapkan pada kenyataan paling sederhana: mencari pekerjaan. Tapi yang ironis, justru di situlah pendidikan berhenti.
Sekolah telah menjadi industri dengan logika sendiri: ada input, proses, output, dan pasar. Seperti industri lain, ia punya rantai produksi: kurikulum disusun, murid dimasukkan, nilai dikeluarkan, ijazah dicetak, dan akhirnya disalurkan ke bursa kerja. Di atas semua itu, berdiri lembaga akreditasi yang berperan seperti dewa penentu kualitas—tanpa pernah menjawab pertanyaan paling mendasar: kualitas untuk apa?
Formalisme menjadi jaring halus yang membungkus segalanya. Murid harus menyesuaikan diri dengan kurikulum, bukan sebaliknya. Seragam menyatukan tubuh tapi meniadakan perbedaan. Semua siswa diajar dengan tempo yang sama, padahal setiap kepala punya irama berpikirnya sendiri. Di sinilah pendidikan berubah dari ruang tumbuh menjadi mesin penyeragaman.
Sekolah, seperti industri mana pun, punya daur hidup: lahir, tumbuh, menua, dan mati. Tapi sekolah kita tampaknya menolak mati. Ia bertahan dengan cara menempel pada sistem kekuasaan. Syarat ijazah diberlakukan untuk hampir semua jabatan publik—terutama PNS. Di situlah rahasia kenapa sekolah tetap ramai dikunjungi: bukan karena orang ingin belajar, tapi karena ingin diakui negara.
Warisan kolonial masih berdenyut di dalamnya. Sejak masa Politik Etis, sekolah didirikan untuk satu tujuan: mencetak pegawai bagi pemerintah penjajah. Kini, tujuan itu diwariskan tanpa penjajah—kita sendiri yang meneruskannya dengan setia. Rekrutmen PNS menjadi upacara nasional: penuh harapan, sogokan, dan kebanggaan palsu. Bahkan muncul bimbingan belajar untuk lolos tes pegawai negeri—sebuah ironi bahwa “pengabdian” pun kini bisa dipersiapkan secara industri.
Sementara itu, sekolah-sekolah menjadi laboratorium kebohongan sosial. Di sana, kejujuran bukan lagi kebajikan, melainkan risiko. “Sing jujur malah ajur,” kata pepatah murid-murid yang sudah belajar bertahan. Menyontek dianggap lumrah, guru lebih cepat marah pada murid yang tak berseragam daripada yang tak membawa pengetahuan. Kekerasan, baik fisik maupun simbolik, menjadi bagian dari atmosfer pendidikan. Sekolah bukan tempat murid belajar, tapi tempat guru mengajar—dua hal yang tak selalu sama.
Semakin lama seseorang bersekolah, semakin jauh ia dari kemandirian. Semakin tinggi ijazah, semakin sulit bekerja tanpa diperintah. Maka lahirlah generasi sarjana yang menganggur, kelas menengah yang konsumtif, dan guru-guru yang diam-diam menjadi pabrik mentalitas pegawai. IKIP yang dulu bangga melahirkan pendidik kini malu mengakuinya, lalu berganti nama menjadi universitas—seolah ganti label bisa menghapus jejak sejarah kolonialnya.
Sekolah pun berhasil menciptakan pengasingan sosial yang halus: anak petani yang cerdas mendapat beasiswa ke fakultas pertanian, lalu kembali dengan jas dan dasi, bukan cangkul. Anak nelayan belajar tentang laut di laboratorium, bukan di dermaga. Akibatnya, desa kehilangan anak-anak terbaiknya, dan laut kehilangan penerusnya.
Kita lupa bahwa sekolah, dalam usia sejarahnya yang baru seabad lebih, hanyalah eksperimen sosial yang muda—produk modernitas Barat yang diperkenalkan lewat kolonialisme. Sebelum itu, kita punya bentuk belajar yang lebih cair: pesantren, padepokan, surau—tempat di mana kerja, ibadah, dan belajar tak pernah dipisahkan. Para pendiri bangsa lahir dari situ: mereka membaca, berdiskusi, berdebat, berjuang—tanpa ijazah, tapi dengan kesadaran.
Barangkali sudah waktunya kita mendefinisikan ulang apa itu pendidikan. Menyelamatkan pendidikan dari persekolahan. Menyelamatkan belajar dari kurikulum. Sebab untuk mendidik manusia, kita tidak perlu tembok, bel masuk, atau formulir kehadiran. Kita hanya perlu ruang—ruang yang membuat setiap orang bisa menjadi guru, sekaligus murid.
Mungkin inilah saatnya kita “menyekolahkan diri dari sekolah”—membebaskan diri dari keyakinan bahwa belajar hanya sah bila disahkan negara. Sebab pengetahuan yang sejati, seperti kehidupan, tak pernah butuh izin.
Nitiprayan, 9 November 2025