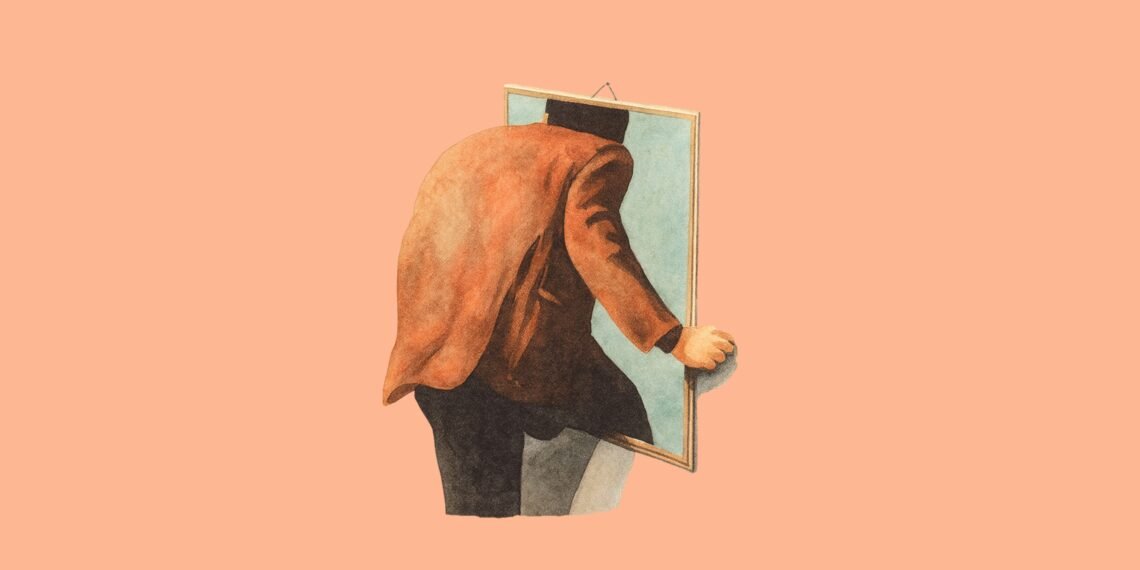DAVID adalah seseorang yang pendiam. Ia sopan kepada orang tua, rajin membantu sesama, dan suaranya jarang terdengar dalam keributan. Tapi begitu membuka media sosial, David berubah. Jempolnya menari lincah, melontarkan kata-kata kasar yang tak pernah terbayang akan keluar dari mulutnya. Dia dengan berani menyerbu kolom komentar, menyebar kebencian, dan merasa itu semua adalah permainan.
Sekitar sepuluh tahun yang lalu, di dunia game online, saya sempat menjadi David dalam bentuk yang lain. Apa yang dimulai sebagai reaksi balas dendam terhadap cacian, berubah menjadi kebiasaan aktif memulai ejekan provokatif. Saat itu, merendahkan orang lain memberi rasa menang yang palsu. Pengalaman itu menunjukkan bahwa David bukanlah monster yang lahir tiba-tiba. Dia adalah produk dari lingkungan digital yang memicu pelepasan diri tanpa batas. Data membenarkan betapa parahnya lingkungan itu di Indonesia.
Pada bulan Februari 2021, Microsoft merilis laporan Digital Civility Index (DCI), sebuah metrik untuk mengukur tingkat interaksi online yang aman dan positif. Indeks ini mengukur seberapa sering pengguna internet mengalami berbagai risiko online, seperti cyberbullying, ujaran kebencian, penipuan, pelecehan seksual, dan penyebaran informasi pribadi. Berdasarkan survei April–Mei 2020, dari 16.000 responden dewasa dan remaja di 32 negara, Indonesia berada di peringkat ke-29, hanya di atas Malaysia, Rusia, dan Arab Saudi — menjadikannya salah satu negara dengan ruang digital paling tidak aman di dunia (Microsoft, 2021).
Ironisnya, banyak warganet justru membuktikan temuan Microsoft itu. Alih-alih introspeksi, mereka menyerbu akun Instagram Microsoft dengan komentar kasar: “Seenaknya lu ya bilang kalo kami gak sopan!” atau “Menilai Indonesia ga sopan… sopankah penilaian itu?” Akhirnya, Microsoft terpaksa menonaktifkan kolom komentar di akun Instagram-nya (Kompas, 2021). Yang menyerbu akun Microsoft mungkin hanya segelintir, tapi suaranya keras. Mereka adalah bayangan dari sebuah ekosistem digital yang memuliakan amarah dan merendahkan empati. Kita menggunakan toksisitas sebagai senjata untuk membela diri dari tuduhan toksisitas. Lingkaran setan yang tak kunjung putus.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Mereka adalah cermin dari transformasi psikologis yang dialami jutaan orang—termasuk saya, dulu, saat menjadi David di dunia game online. Perubahan drastis semacam itu bukan sihir. Ini gejala dari transformasi psikologis yang dialami jutaan warganet.
Peristiwa seperti itu terjadi setiap hari di sudut-sudut media sosial. Anonimitas online bukan sekadar fitur teknis; ia adalah kondisi psikologis kuat yang mengubah siapa kita. Psikolog John Suler, memberikan nama yang tepat untuk menggambarkan gejala dari sebuah kondisi psikologis yang dalam ini: Online Disinhibition Effect (ODE). Sebuah kondisi di mana seseorang merasa lebih nyaman dan lepas untuk mengekspresikan diri—baik untuk hal baik maupun buruk—saat berkomunikasi secara online dibandingkan di dunia nyata. Suler membedakan dua wajah dari fenomena ini.
Pertama, adalah Benign Disinhibition. Ini adalah sisi terangnya. ODE jenis ini memudahkan seseorang mengekspresikan perasaan, harapan, dan melakukan hal-hal positif yang mungkin malu dilakukannya secara offline. Bayangkan seorang remaja pemalu yang akhirnya berani membagikan puisi karyanya, atau seorang korban kekerasan yang menemukan keberanian untuk bercerita di forum anonim. Ini adalah anonimitas yang membebaskan.
Kedua, wajah yang lebih sering kita jumpai: Toxic Disinhibition. Inilah yang dialami oleh David dan para perusuh kolom komentar di banyak platform media sosial. ODE toksik adalah pelepasan emosi negatif seperti kemarahan, hujatan, ancaman, atau ujaran kebencian yang jarang muncul dalam interaksi langsung. Ini adalah wajah internet yang sering kita temui: kolom komentar penuh hinaan, cyberbullying, atau perusuh kolom komentar, yang di dunia nyata mungkin orang biasa, tapi di dunia maya menjadi agresor tanpa belas kasihan.
Lalu, apa yang memicu seseorang memilih jalur toksik daripada yang positif dalam interaksi di dunia maya? Jawabannya terletak pada dua variabel kunci: anonimitas dan konsep diri.
Anonimitas ibarat topeng di dunia nyata, ia dapat digunakan untuk tarian atau untuk perampokan. Pilihan moral memang sepenuhnya ada di individu. Tetapi sering kali, anonimitas bukan pilihan, melainkan strategi bertahan hidup bagi yang rentan, atau senjata sistemik bagi yang dominan.
Di balik layar, anonimitas menciptakan jarak psikologis antara identitas digital dan dunia nyata. Perlindungan ini memberi rasa aman dari konsekuensi sosial, sehingga individu merasa bebas melepaskan dorongan yang biasanya mereka tahan di dunia nyata. Fenomena ‘second account’, misalnya, menjadi ruang eksperimen identitas di kalangan muda yang berfungsi sebagai alter ego digital—sebuah sandbox pribadi tempat mereka bisa bereksperimen dengan identitas tanpa pengawasan. Di sini, mereka bisa mengikuti konten yang dianggap tabu, mengungkapkan opini kontroversial, atau sekadar menjadi “sosok lain”. Eksperimen identitas semacam ini wajar dalam masa pencarian diri, tetapi bisa berbahaya jika tidak diimbangi kesadaran moral.
Namun, anonimitas juga punya sisi terang. Dalam konteks yang tepat, ia bisa menjadi alat perlindungan yang kuat. Edward Snowden, misalnya, memanfaatkan anonimitas untuk membocorkan praktik pengawasan massal NSA—tindakan yang dilihat banyak pihak sebagai bentuk pembelaan kebenaran, meski secara hukum masih diperdebatkan. Demikian pula dalam forum dukungan mental atau konseling daring, anonimitas justru mendorong keterbukaan. Studi Prescott, Hanley, dan Ujhelyi (2018) menunjukkan bahwa kerahasiaan meningkatkan partisipasi aktif dan membuat seseorang merasa cukup aman untuk berbagi trauma atau masalah pribadi. Dalam kasus ini, anonimitas bukan pelindung bagi pelaku toksik, melainkan selimut bagi yang rentan.
Selain anonimitas, faktor penentu lainnya adalah konsep diri. Konsep diri adalah cara seseorang memandang dirinya secara fisik, mental, dan sosial. Carl Rogers membaginya menjadi real self (diri yang sebenarnya) dan ideal self (diri yang ingin dicapai). Nah, masalah besar muncul ketika terjadi kesenjangan lebar antara real self dan ideal self. Ingin dianggap percaya diri, tapi merasa pemalu. Ingin terlihat keren, tapi penuh keraguan. Konflik antara ideal self dan real self inilah yang membuat media sosial menjadi panggung ilusi. Media sosial kemudian menjadi panggung sempurna untuk menutupi kesenjangan ini. Di sini, mereka dapat dengan mudah membangun dan menampilkan ideal self mereka tanpa halangan. Mereka menjadi “versi terbaik” yang sebenarnya adalah ilusi.
Gabungan antara anonimitas dan ketidakselarasan konsep diri menciptakan kondisi sempurna untuk toxic disinhibition. Beberapa faktor memperkuat efek ini: kita merasa tak dikenali, tak terlihat, dan tak harus langsung menghadapi reaksi. Kita membayangkan lawan bicara sesuai imajinasi sendiri, menganggap dunia maya sebagai ‘realitas alternatif’, dan merasa otoritas sosial jauh — sehingga norma pun longgar. Semua elemen ini bersatu, membentuk lingkungan yang memudahkan seseorang untuk melepaskan sisi gelap dirinya tanpa rasa malu.
Dengan demikian, pilihan antara perilaku positif dan toksik di dunia maya bukan semata soal teknologi, melainkan cerminan dari dinamika psikologis dalam diri. Anonimitas memberi sarana, tetapi konsep diri menentukan arahnya. Jika didukung oleh kesadaran diri dan empati, internet bisa menjadi ruang penyembuhan dan pertumbuhan. Namun jika digunakan untuk menghindari realitas atau melampiaskan frustrasi, ia berubah menjadi medan toksisitas yang merusak.
Lantas, bagaimana kita menjinakkan dunia maya? Solusinya tidak bisa hitam putih. Menghapus anonimitas sama sekali adalah kekeliruan besar karena sama saja dengan membungkam suara-suara rentan yang justru paling membutuhkannya. Sebaliknya, kita perlu pendekatan yang multi-layer.
Teknologi seperti blockchain bisa jadi visi masa depan: sistem reputasi digital yang melacak perilaku tanpa membocorkan identitas. Rancangan filosofis platform juga bisa menjadi alternatif solusi jangka panjang. Kita memerlukan bangun ruang digital yang tidak memonetisasi amarah dan kebencian, melainkan didasarkan pada prinsip ‘anonimitas bertanggung jawab’—seperti yang sudah dilakukan pada forum support group untuk trauma survivor atau jaringan whistleblower.
Tapi hari ini, solusi terdekat adalah kesadaran akan prinsip sederhana: sebelum posting, kita perlu membangun kebiasaan untuk berpikir ulang dan bertanya pada diri sendiri, “Apakah saya akan berkata seperti ini jika nama saya terlampir? Apakah ini mencerminkan ideal self, atau justru melukiskan real self yang paling buruk?”
Di sisi lain, komentar akun anonim sering kali sengaja dirancang untuk memancing emosi. Menahan diri dari balas dendam atau debat panas adalah langkah awal yang bijak. Berhenti sejenak sebelum merespons bisa mencegah kita ikut tenggelam dalam siklus negativitas. Tetapi, meski komentar datang dari akun anonim, tanyakan juga: apakah ada benarnya? Apakah kritik tersebut membawa masukan yang konstruktif? Jika iya, bisa diambil sebagai refleksi tanpa perlu menyerang balik. Namun jika isinya hanya hujatan atau fitnah, maka lebih baik diabaikan.
Kita tidak bisa terus menyalahkan anonimitas. Dengan berkomentar secara bijak, sopan, dan bertanggung jawab dengan akun anonim, kita memberi contoh bahwa anonimitas bukan alasan untuk tidak bermoral. Perilaku positif bisa menular, bahkan di dunia maya. Anonimitas yang sejati bukanlah tentang menyembunyikan diri untuk menyerang. Ia adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri tanpa rasa takut, sebuah ruang aman untuk tumbuh—bukan untuk menghancurkan. Mungkin David tidak menyadarinya saat itu. Tapi sekarang kita semua bisa memulai kesadaran itu dari diri masing-masing, sebelum dunia maya semakin menjadi medan perang permanen yang akan kita sesali sendiri.