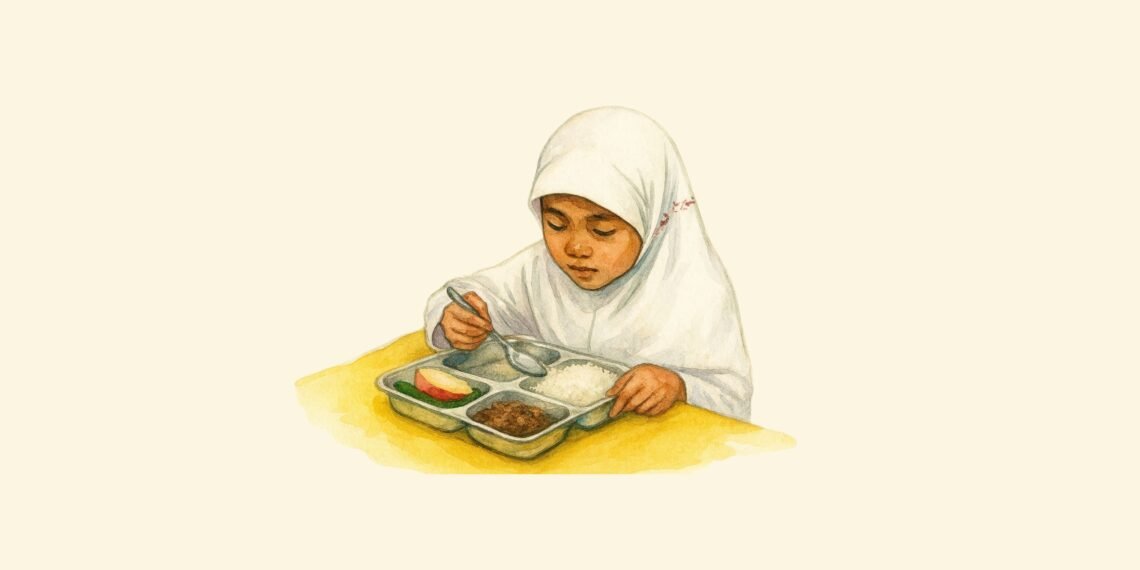DI SEBUAH ruang kelas sederhana, sepiring nasi hangat dan sepotong lauk pernah menjadi jembatan antara mimpi seorang anak dan nasib sebuah bangsa. Program makan sekolah, yang bagi sebagian orang tampak remeh, sejatinya adalah cermin dari bagaimana sebuah negara memperlakukan masa depannya sendiri. Apakah ia menaruh perhatian pada perut anak-anak, ataukah membiarkan mereka tumbuh dengan rasa lapar yang diam-diam meluruhkan harapan?
Sejarah panjangnya berawal jauh dari sini. Di Inggris abad ke-19, ketika pabrik-pabrik mengepulkan asap dan kota-kota dipenuhi buruh cilik dengan wajah pucat, makan sekolah lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari belas kasihan. Gereja dan para filantropis berusaha memberi makan anak-anak yang terlalu lemah untuk belajar. Namun negara akhirnya sadar: kesehatan publik tak bisa diserahkan pada kemurahan hati individu.
Lahirnya Education (Provision of Meals) Act 1906 menandai pergeseran penting—makan di sekolah bukan lagi amal, melainkan hak sosial. Di atas meja makan sederhana itu, negara berjanji bahwa tak seorang anak pun boleh belajar dalam keadaan perut kosong. Janji itu menggema hingga kini, di berbagai belahan dunia. Di Jepang, makan siang sekolah disusun sebagai bagian kurikulum—anak-anak belajar menghargai makanan, alam, dan kerja kolektif. Di Brasil, program makan sekolah digandengkan dengan petani lokal, sehingga gizi anak-anak sekaligus menghidupkan ekonomi desa. Makanan menjadi simpul solidaritas, bukan sekadar angka kalori.
Namun di banyak tempat lain, termasuk negeri kita, makan sekolah sering terjebak di persimpangan: apakah ia sekadar proyek tender, ladang bisnis katering, atau sungguh menjadi media pendidikan kebersamaan dan martabat? Pertanyaan itu tak sederhana. Sebab di balik sepiring nasi, tersembunyi logika politik: apakah negara melihat anak-anak sebagai investasi jangka panjang atau sekadar beban anggaran? Apakah keadilan bisa dihidangkan bersama lauk sederhana di piring plastik?
Anak-anak itu, dengan seragam lusuh dan sandal jepit, sebenarnya sedang menguji janji negara. Setiap kali mereka menerima atau tidak menerima makanan bergizi di sekolah, yang dipertaruhkan bukan hanya kenyang atau lapar, melainkan hakikat demokrasi itu sendiri—apakah ia hadir untuk melindungi yang paling lemah, atau hanya untuk melayani mereka yang sudah kenyang.
Mungkin, seperti di Inggris seabad silam, kita sedang menunggu sebuah keberanian politik: keberanian untuk berkata bahwa sepiring nasi di sekolah bukanlah kemurahan hati pemerintah, melainkan hak yang melekat pada martabat setiap anak.
Di Amerika Serikat, setelah perang dunia usai, sepiring makan siang anak-anak membawa beban ganda: menyembuhkan tubuh mungil yang ringkih sekaligus menyalurkan surplus jagung, gandum, dan susu dari ladang-ladang industri. National School Lunch Act 1946 menjadi penanda bahwa negara dapat memelihara rakyat kecil sambil tetap menjaga kepentingan pasar domestik. Politik pangan dan politik gizi berjalan bergandengan, dan di ruang kelas, anak-anak menjadi penerima sekaligus penopang sistem ekonomi.
Di Jepang, yang luluh lantak oleh bom dan kekalahan, makan siang sekolah diperlakukan seperti ritual rekonstruksi bangsa. Bukan hanya mengenyangkan, melainkan mendidik: shokuiku—pelajaran hidup melalui makanan. Anak-anak tidak sekadar makan, tetapi belajar menata meja, menghargai petani, memahami musim, dan bersyukur pada alam. Dari suapan kecil itu, Jepang menanamkan fondasi karakter kolektif yang membuat mereka bangkit dari reruntuhan.
Skandinavia memilih jalur yang berbeda. Sejak 1940-an, Finlandia dan Swedia memutuskan: semua anak berhak atas makan gratis, tanpa membedakan kaya atau miskin. Di sana, makan siang menjadi bahasa paling sederhana dari negara kesejahteraan: keadilan yang bisa disentuh, ditelan, dan dirasakan setiap hari.
India, negeri dengan sejarah panjang kelaparan, menjadikan Mid-Day Meal Scheme sebagai undangan terselubung agar anak-anak miskin datang ke sekolah. Sepiring kacang lentil atau nasi kari adalah cara negara berkata: belajarlah, karena di sini kau akan kenyang.
Brasil melangkah lebih jauh. Undang-undang mereka mewajibkan tiga puluh persen bahan pangan makan sekolah dibeli dari petani kecil. Dengan begitu, meja makan anak-anak sekaligus menjadi ladang subur bagi kedaulatan pangan dan pemberdayaan desa.
Masing-masing bangsa meramu cara sendiri, tapi benang merahnya sama, menyediakan makan sekolah adalah cermin politik. Ia bisa menjadi saluran surplus industri, alat rekonstruksi budaya, simbol kesejahteraan universal, instrumen melawan kelaparan, atau strategi memberdayakan desa. Di balik semua itu, ada pertanyaan yang menunggu dijawab oleh setiap negeri. Ketika anak-anak duduk lapar di ruang kelas, sejauh mana negara rela menaruh masa depannya di atas meja makan sederhana?
Pola-pola itu memperlihatkan satu benang merah: program makan sekolah bukan sekadar soal dapur, melainkan arah politik yang terukur. Konsisten dengan gagasan mission-oriented policy (Mazzucato, 2018), makan sekolah menjadi cermin misi sebuah bangsa—bukan proyek teknokratis jangka pendek, bukan pula populisme yang cepat menguap.
Inggris dan Amerika menempatkannya sebagai instrumen kesehatan publik sekaligus penyangga stabilitas pangan. Jepang meramunya menjadi fondasi nation-building dan pendidikan nilai, di mana setiap butir nasi adalah pelajaran tentang kebersamaan. Skandinavia menegaskannya sebagai ekspresi paling konkret dari kesetaraan sosial: keadilan yang hadir di piring, bukan sekadar di konstitusi. India, dengan luka sejarah kelaparan, menjadikannya umpan harapan agar anak-anak mau belajar. Brasil—mungkin yang paling radikal—menyulamnya dengan kedaulatan pangan, memberdayakan petani kecil sekaligus memberi makan anak bangsa.
Dari sana kita belajar bahwa sepiring makanan di sekolah adalah instrumen moral, politik, dan peradaban. Ia adalah janji jangka panjang, arah visi sebuah bangsa: apakah negara hanya mengukur masa depan dengan angka pertumbuhan, ataukah dengan wajah anak-anak yang bisa belajar tanpa rasa lapar.
Di banyak negara, sepiring makan siang di sekolah merupakan simbol keseriusan negara menjaga generasinya. Di Jepang, misalnya, kyūshoku bukan sekadar rutinitas makan bersama, tetapi pendidikan hidup: anak-anak diajarkan menakar nasi, menyendok sup, membagi lauk pada teman sekelas. Mereka belajar kebersamaan, disiplin, dan kesadaran bahwa pangan adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Makan siang menjadi kelas sunyi tentang hormat pada tubuh, pada bumi, pada petani.
Bandingkan dengan negeri ini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) datang dengan gegap gempita politik, tetapi rapuh di akar. Tidak ada peta jalan, tidak ada kerangka besar yang menautkan program ini dengan nasib petani kecil yang tiap musim bergulat dengan harga jatuh. Tidak ada ruang bagi sekolah untuk menjadikan makan bersama sebagai kurikulum nilai. Anak hanya dijanjikan kenyang, padahal kenyang semu sering menyembunyikan lapar yang lebih dalam: lapar akan penghargaan, lapar akan martabat, lapar akan masa depan.
Saya teringat seorang ibu di pelosok Jawa. Ia bercerita tentang anaknya yang saban hari berangkat sekolah hanya dengan bekal singkong rebus. Ketika mendengar kabar akan ada “makan gratis”, wajahnya berbinar. Tetapi kemudian ia mendengar bahwa makan siang anaknya akan diurus perusahaan katering besar di kota. “Lalu, kami para petani kecil, apa gunanya lagi?” tanyanya. Pertanyaan itu, yang lahir dari bibir seorang perempuan desa, lebih tajam daripada riset manapun.
Di sinilah paradoks itu bersemayam: program yang seharusnya merangkul justru berjarak. Negara lupa bahwa makanan adalah narasi tentang hubungan paling intim antara bumi dan manusia. Ia bukan sekadar kontrak tender, melainkan kontrak moral. Bila negara gagal menjahitnya, yang lahir hanyalah piring hampa: penuh nasi, kosong makna.
Sejarah pernah mengajarkan bahwa bangsa yang gagal memberi makan dengan martabat pada anak-anaknya, lambat laun akan kehilangan arah. Karena anak-anak yang tumbuh tanpa penghormatan pada pangan akan menjadi dewasa yang asing pada tanahnya sendiri.
Lebih tragis lagi, tragedi keracunan yang menimpa lebih dari lima ribu anak telah menorehkan luka yang tak bisa disembunyikan oleh statistik. Angka itu bukan sekadar persentase dalam laporan resmi. Ia punya wajah, punya tubuh kecil yang menggigil, punya mata yang ketakutan menatap piring makan. Di banyak desa, cerita yang beredar bukan tentang “makan bergizi”, melainkan tentang anak-anak yang muntah di kelas, pingsan di halaman sekolah, atau terbaring di rumah sakit dengan selang infus menusuk tangan mungil mereka.
Namun negara memilih bahasa yang dingin: 0,00017 persen. Sebuah reduksi yang kejam, seolah tubuh-tubuh kecil itu hanyalah angka cacat produksi. Padahal setiap anak adalah dunia utuh dengan impian yang belum sempat tumbuh. Politik tanpa empati selalu pandai mencari angka untuk menutupi luka, tetapi selalu gagal menutup jeritan.
Di balik itu, lahirlah pola tata kelola yang kian absurd: sentralistik dan militeristik. Semua dikendalikan dari pusat, seakan anak-anak di sekolah hanyalah pion dalam papan catur kebijakan. Yang dikedepankan bukan kelembutan merawat, melainkan disiplin menundukkan. Seperti barisan tentara kecil yang harus makan apa yang disuapkan negara, meski lidah mereka menolak, meski perut mereka memberontak.
Ilmu pengetahuan tak diberi ruang. Tidak ada riset yang matang, tidak ada uji coba sosial, tidak ada percakapan dengan para petani, guru, apalagi anak-anak itu sendiri.
Program ini berlari kencang hanya demi satu tujuan, yakni pertunjukan politik. Apa yang dipertontonkan ke publik adalah piring yang tampak penuh. Tetapi yang tidak ditunjukkan adalah bahwa piring itu rapuh, dan di bawahnya berderet tubuh kecil yang meringis kesakitan.
Seorang guru di Sulawesi berkata, “Anak-anak ketakutan setiap kali jam makan siang tiba. Mereka bilang, makanan gratis itu seperti undian: kita tidak tahu kapan akan jatuh sakit.” Kalimat itu seharusnya cukup untuk membuat negara berhenti sejenak, menunduk, dan bercermin. Tetapi yang terdengar hanyalah gema pidato tentang target dan persentase.
Begitulah yang seharusnya menjadi simbol pelayanan negara justru berubah menjadi sumber trauma. Sejarah mungkin akan mencatat program ini bukan sebagai tonggak peradaban, melainkan sebagai ironi: ketika bangsa menjanjikan gizi, tetapi justru menabur racun ke tubuh anak-anaknya sendiri.
Ironinya, inisiatif-inisiatif lokal yang selama ini berjalan penuh cinta justru dipaksa berhenti. Di Solo, misalnya, sebuah sekolah Muhammadiyah telah lama mengelola dapur sehat berbasis partisipasi orang tua dan guru. Di sana, makanan bukan sekadar lauk dan nasi, tetapi buah dari musyawarah: ada ibu yang menanam sayur di pekarangan, ada ayah yang memasok telur dari peternakan kecilnya, ada guru yang menambahkan pengetahuan tentang gizi. Piring anak-anak berisi bukan hanya makanan, tetapi juga cerita tentang tangan-tangan yang bergotong royong. Semua itu lenyap ketika MBG datang dengan label “program nasional”.
Dapur yang pernah jadi ruang dialog kini digantikan dengan makanan massal dari vendor instan. Nasi datang dalam kotak yang sama, lauk bercita rasa pabrik, buah dipotong tergesa, tanpa aroma tanah tempat ia tumbuh. Orang tua mulai resah. “Kalau anak saya keracunan, siapa yang bertanggung jawab?” begitu pertanyaan yang berulang terdengar.
Di banyak sekolah, rantang kosong mulai bermunculan. Bukan untuk mengisi, melainkan untuk menyingkirkan makanan yang tidak mereka sukai. Anak-anak belajar diam-diam membuang makanan gratis—sebuah ironi yang lebih pahit daripada kelaparan. Karena apa artinya kenyang, bila tubuh menolak suapan yang dipaksakan?
Guru pun ikut menanggung beban. Mereka yang seharusnya fokus mendidik kini harus berjibaku menerima kiriman makanan, mengatur pembagian, memastikan wadah kembali utuh, bahkan menanggung kerugian bila ada kehilangan. Parahnya, setiap kali kasus keracunan muncul, guru dijadikan kambing hitam: dituding lalai, padahal mereka hanya pelaksana di garis depan.
Sementara itu, UMKM lokal terpaksa menutup pintu, petani tetap menjual hasil panen dengan harga murah, dan pemerintah daerah menjalankan program ini dengan keterpaksaan yang nyaris telanjang. Yang tersisa hanyalah ketidakpercayaan: pada makanan yang disajikan, pada program yang dicanangkan, bahkan pada negara yang seharusnya melindungi.
Lebih dalam, tata kelola MBG benar-benar menyerupai labirin yang gelap. SPPG, para penyedia lapangan, dituntut memasak ribuan paket dalam sehari—hingga tiga ribu dalam sekali putaran. Dapur mereka dipaksa menyala sejak tengah malam, ketika sebagian besar anak masih bermimpi. Dari kuali yang bekerja terburu-buru, lahirlah makanan yang tidak segar, menunggu berjam-jam di udara lembab, menanggung risiko kontaminasi bakteri. Dari situ, lahir pula keracunan yang merayap pelan ke tubuh anak-anak.
Tidak ada keterhubungan dengan petani lokal—mereka yang seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan pangan. Justru yang muncul adalah persaingan sengit di pasar. Ada laporan petani yang didatangi langsung di kebun, dipaksa menjual hasil panennya dengan harga ditekan. Proses pengadaan ini dipenuhi nuansa militeristik: kasar, satu arah, menyingkirkan dialog. Sentralisme dan militerisme yang dilembagakan menjadikan program ini miskin akuntabilitas, anti partisipasi, dan melecehkan ilmu pengetahuan. Inilah “racun” tata kelola yang paling berbahaya—racun yang tidak tampak di piring, tetapi menetes ke dalam sistem.
Produksi skala ribuan paket diperlakukan seolah pesta hajatan: tanpa teknologi pendukung, tanpa gudang penyimpanan, tanpa infrastruktur yang layak, tanpa tenaga ahli gizi, tanpa imajinasi menu yang hidup. Distribusi pun serampangan, penuh kerumitan administratif, tak pernah memperhitungkan keragaman konteks lokal.
Maka lahirlah menu-menu yang aneh dan ironis: burger dingin di sekolah pedesaan, sandwich hambar di tepi ladang padi, bahkan ikan hiu—spesies langka yang dijadikan santapan dengan dalih “kearifan lokal”. Setiap piring bukan hanya mengandung kalori, tetapi juga absurditas.
Semua ini bukan sekadar deretan kesalahan teknis. Ia adalah cermin keangkuhan penguasa, yang lebih sibuk mengejar pujian ketimbang mendengarkan jeritan. Ia adalah buah keterburuan politik yang rakus akan sorak-sorai, tetapi hampa akan sains, riset, dan kerendahan hati dalam merencanakan. Yang paling tragis, anak-anaklah yang menjadi tubuh percobaan, saksi bisu atas sebuah negara yang lupa, bahwa memberi makan bukanlah soal kuantitas, melainkan soal martabat.
Di balik kekacauan itu, aroma rente menyeruak lebih pekat daripada bau nasi yang basi. Kontrak-kontrak vendor terjalin dalam jejaring kekuasaan, dapur instan disulap tanpa standard, ompreng impor murah dari Tiongkok dibagikan dengan kabar samar: konon mengandung minyak babi. Di ruang kelas, anak-anak mungkin tak tahu persis apa yang sedang terjadi. Tetapi tubuh mereka yang sakit, rasa takut yang mereka simpan, adalah bukti paling jujur bahwa ada sesuatu yang busuk di dapur kebijakan negeri ini.
Guru dan sekolah ditekan untuk diam. Jangan unggah foto menu, jangan bercerita tentang keracunan, jangan menyinggung kegagalan. Lidah yang ingin bersuara dipaksa bungkam, demi keberlangsungan proyek. Dalam sunyi itulah, MBG berubah wajah: bukan lagi program gizi, melainkan arena represi.
Maka jelas, ini bukan hanya krisis nutrisi. Ia telah menjelma menjadi krisis tata kelola, krisis moral, krisis kepercayaan—bahkan, pelan-pelan, krisis kemanusiaan. Jika dibiarkan, MBG akan dikenang sebagai sebuah policy catastrophe—kebijakan yang lahir dengan retorika seolah mulia, tetapi justru menimbulkan bencana sosial. Sejarah akan menuliskannya sebagai contoh betapa mudah politik mengkhianati anak-anak, betapa cepat janji bergizi berubah menjadi racun.
Satu-satunya jalan rasional adalah menghentikan program ini dalam bentuknya yang sekarang, lalu merancang ulang dengan visi yang lebih manusiawi. Sebuah desain yang berangkat dari filosofi kasih sayang (caring), bukan paksaan (control); yang membuka ruang partisipasi, bukan menutup rapat kendali; yang menyadari bahwa memberi makan anak adalah pekerjaan paling sakral, bukan panggung pertunjukan.
Ketika sebuah bangsa benar-benar tulus memberi makan anak-anaknya, sesungguhnya ia sedang memberi makan dirinya sendiri—memberi makan jiwa kolektif yang letih, yang haus akan keadilan, yang rindu pada kasih.
Empat lapisan kunci harus menjadi fondasi transformasi sehingga program ini bukan sekadar program makan siang, melainkan gerakan peradaban yang utuh.
Pertama, dengan benar-benar mendengar dunia anak—dunia yang polos namun jujur, dunia di mana rasa dan psikologi makan sama pentingnya dengan gizi. Anak-anak harus diperlakukan sebagai subyek aktif: apa yang mereka sukai, apa yang mereka percayai, apa yang membuat mereka merasa dihormati.
Kedua, sekolah mesti menjadi ekosistem hidup. Dapur sehat bukan sekadar ruang memasak, tetapi ruang belajar bersama tentang nutrisi, kebersihan, dan siklus kehidupan. Sisa makanan yang dulunya terbuang bisa diolah kembali, menjadi kompos, memberi makan tanah, dan menumbuhkan sayur yang esok kembali ke piring anak.
Ketiga, UMKM lokal, dapur komunitas, para ibu yang berpengalaman, dan para ahli gizi yang berkomitmen, harus menjadi mitra utama. Bukan vendor instan yang datang dengan kontrak besar, lalu pergi meninggalkan trauma. Dari tangan-tangan kecil komunitas inilah lahir inovasi: resep baru, menu sehat, cara sederhana namun bermakna menjaga kualitas pangan.
Keempat, jembatan harus dibangun antara sekolah dan petani lokal. Supaya anak-anak tahu bahwa nasi yang mereka makan pernah tumbuh di sawah desa sebelah, sayuran berasal dari kebun tetangga, telur dari ayam yang mereka dengar berkokok setiap pagi. Hubungan ini bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi pendidikan ekologis: makanan adalah mata rantai yang menyatukan manusia dengan bumi.
Semua lapisan itu harus berdiri di atas satu kerangka besar: ekosistem pangan sehat sekolah, berbasis sains, inovasi, dan partisipasi masyarakat.
Karena itu, program makan sekolah hanya bisa berhasil bila ditransformasikan dari proyek politik menjadi proyek pengasuhan. Anak-anak bukan objek, mereka adalah pusat. Ibu-ibu, guru, komunitas lokal, dan ilmuwan lintas disiplin harus dilibatkan penuh. Diversitas Indonesia, yang begitu kaya, tidak boleh dipaksa menjadi menu homogen dalam kotak seragam.
Militer dan polisi harus ditarik keluar dari dapur sekolah. Paksaan harus diganti dengan partisipasi, tekanan diganti dengan inovasi. Tata kelola nasional harus bersandar pada sistem berbasis data, dashboard evaluasi, serta pengawasan yang transparan. Karena tanpa sains, tanpa kasih, tanpa partisipasi—kegagalan program ini bukan soal “jika”, melainkan soal “kapan.”
Pada akhirnya, makan sekolah memang bukan perkara sepiring nasi dan lauk sederhana. Ia adalah cermin kemanusiaan kita, tolok ukur apakah bangsa ini sungguh-sungguh menaruh hormat pada masa depan. Bagaimana kita memberi makan anak-anak hari ini akan menentukan wajah esok: apakah penuh cahaya atau justru buram dan pincang.
MBG hari ini bukan hanya gagal memberi nutrisi, tetapi juga gagal memberi rasa aman, gagal memelihara kepercayaan. “Bergizi” ternyata bisa berarti keracunan; “gratis” ternyata berbiaya fantastis dari APBN, dari keringat pajak rakyat. Nama yang manis justru menutupi rasa getir di baliknya.
Dari janji mulia, yang tersisa hanyalah pengkhianatan—pengkhianatan yang begitu telanjang karena merendahkan kemuliaan anak dan sekolah. Negara lupa, bahwa di balik setiap piring makanan, terselip doa orang tua: doa agar anak-anak mereka tumbuh sehat, belajar dengan tenang, dan kelak menjadi manusia yang patut.
Jika kita sungguh ingin menghindari krisis yang lebih dalam, jalan satu-satunya adalah mengembalikan makan sekolah pada esensinya: memuliakan anak-anak, menjaga tubuh dan jiwa mereka, menumbuhkan generasi dengan penuh cinta, berbasis sains, dan ditopang keadilan sosial.
Selebihnya, sejarah akan mencatat: bangsa ini pernah tergoda menjadikan anak-anak sebagai panggung politik. Di udara, tersisa satu pertanyaan yang menggantung: akankah kita belajar dari luka ini, atau sekali lagi membiarkan generasi yang belum selesai tumbuh menanggung beban dosa orang dewasa?
Nitiprayan, 30 September 2025