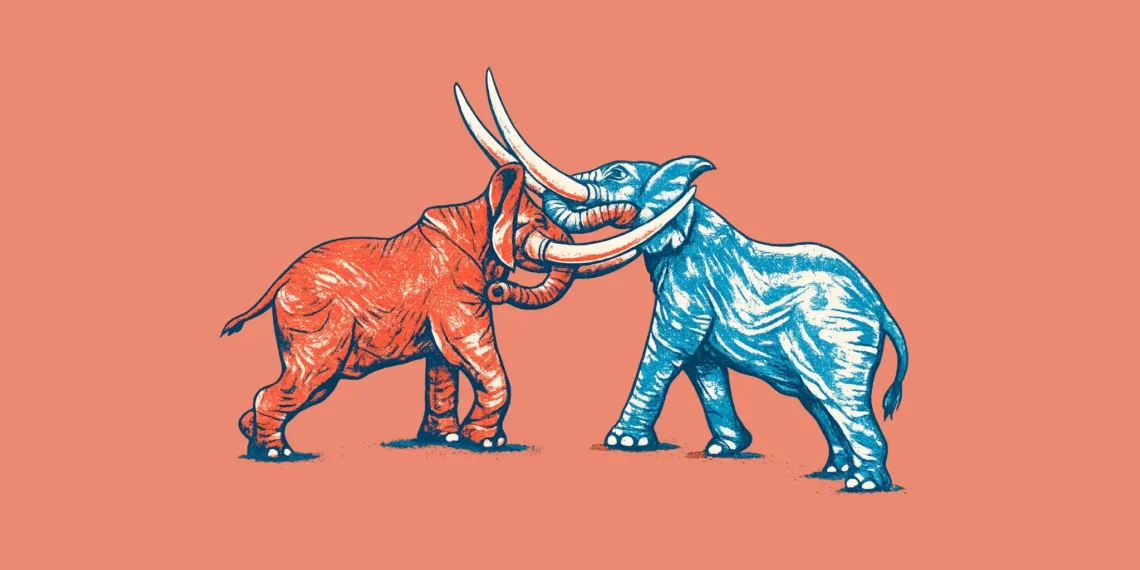SEJARAH, kata orang, tak pernah berulang. Ia hanya menukar wajah, seperti aktor lama yang muncul kembali dengan riasan baru. Tahun 2026—jika kelak dicatat—barangkali bukanlah sebuah permulaan. Ia lebih mirip catatan kaki dari sebuah kisah panjang yang kita pura-pura lupa, padahal masih kita hidupi.
Di panggung dunia, dua gajah kembali saling berhadapan. Yang satu tua, berisik oleh ingatan tentang kejayaan, membawa luka-luka perang yang disamarkan sebagai moral. Yang lain lebih muda, bergerak pelan, nyaris tanpa pidato, tetapi tubuhnya tumbuh tanpa meminta izin. Amerika dan Cina. Seperti pepatah lama yang terlalu sering kita kutip tanpa sungguh memikirkannya: ketika gajah bertarung, rumputlah yang hancur. Rumput itu bukan metafora yang jauh. Ia adalah kita.
Konflik global hari ini bukanlah dentuman mendadak. Ia adalah bunyi retak—halus dan nyaris sopan—dari tulang-tulang kekuasaan yang menua. Amerika, yang dulu menulis arah sejarah dengan tinta tebal, kini sibuk mengejar bayangannya sendiri: utang yang menumpuk seperti arsip tak terbaca, legitimasi moral yang bocor, dan kelelahan memainkan peran sebagai polisi dunia. Namun kekuasaan, seperti manusia yang menua, jarang mau menerima cermin. Ia lebih suka memecahkannya.
Perang Ukraina adalah etalase paling terang. Papan catur dibentangkan, pion-pion digeser, lalu dikorbankan. NATO bergerak, sanksi dijatuhkan, retorika moral diulang seperti doa. Tapi sejarah, yang bandel, menolak patuh pada skenario. Rusia tidak runtuh. Ia justru menemukan kembali naluri purbanya: bertahan. Upaya melemahkan Moskow demi memutus simpul Cina–Rusia tampak seperti menimba laut dengan ember berlubang.
Ironi bekerja tanpa suara. Setiap tekanan justru mempercepat apa yang ingin dicegah. Dua negara yang dulu saling curiga kini belajar satu bahasa yang paling jujur: bahasa kepentingan. Amerika lupa satu pelajaran tua yang selalu muncul dalam buku-buku sejarah yang jarang dibaca ulang: musuh bersama adalah guru persahabatan paling efektif.
Maka tahun 2026—jika kita berani meminjam kacamata masa lalu—bukanlah tahun ledakan, melainkan tahun pengakuan. Pengakuan bahwa dunia tak lagi bisa dipaksa berjalan satu arah. Bahwa hegemoni bukan hukum alam, melainkan kontrak sosial yang punya tanggal kedaluwarsa. Amerika masih kuat, tentu. Tapi kekuatannya kini seperti matahari sore: terang, hangat, sekaligus condong ke barat.
Cina bergerak dengan cara lain. Ia seperti air—tak selalu menghantam, tapi mengikis. Ia tahu waktu adalah sekutu mereka yang tak tergesa. Dalam kesabaran itu, Washington membaca ancaman. Dalam ketenangan itu, Amerika melihat bahaya. Padahal, kekuasaan selalu rapuh justru ketika ia ingin tampak abadi.
Peta dunia hari ini, jika dibentangkan di lantai, menyerupai tubuh yang tegang. Timur Tengah, Laut Cina Selatan, Afrika, Amerika Latin—semuanya berdenyut dalam irama yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini orkestrasi kecemasan sebuah kekuatan yang takut kehabisan napas.
Minyak, dalam drama ini, bukan sekadar cairan hitam. Ia adalah darah modernitas. Siapa menguasai alirannya, menguasai denyut kehidupan. Maka Timur Tengah dijaga tetap panas, seolah-olah api di sana adalah kondisi alamiah. Lewat sekutu lama yang tak pernah sungguh netral, gangguan suplai energi menjadi strategi klasik untuk mengacaukan perut industri Cina.
Laut Cina Selatan pun tak sesederhana sengketa karang. Yang diperebutkan bukan batu, melainkan Selat Malaka—leher botol dunia, tempat tanker-tanker minyak melintas seperti nadi terbuka. Menguasainya berarti memiliki tangan di tenggorokan Beijing. Dalam geopolitik, mencekik pelan sering lebih efektif daripada memukul keras.
Venezuela masuk bab yang sama. Demokrasi, di sini, hanyalah kata sandi. Yang sesungguhnya diperebutkan adalah cadangan minyak terbesar di dunia. Sanksi, delegitimasi, ancaman—semua dirangkai untuk satu tujuan sederhana: jangan biarkan energi jatuh ke tangan pesaing.
Namun cerita tak berhenti pada minyak. Bab berikutnya ditulis dengan bahan yang lebih sunyi: rare earth elements. Afrika dan Amerika Selatan kembali menjadi panggung instabilitas. Kudeta kecil, konflik berkepanjangan, ketegangan yang disebut “organik”. Semua bekerja seperti pasir di mesin, mengganggu akses Cina pada mineral yang menopang teknologi masa depan.
Inilah perang tanpa deklarasi. Tanpa meriam. Tanpa parade kemenangan. Tapi dampaknya merayap ke mana-mana. Rantai pasok terganggu, pelabuhan tersendat, pabrik melambat. Dunia gaduh, dan dalam kegaduhan itu, mesin ekspor Cina diharapkan tersendat.
Kekuasaan, ketika terancam, selalu memilih merusak meja daripada berbagi kursi.
Di Amerika sendiri, panggung mulai retak. Kerusuhan dan perang sipil tak lagi sepenuhnya fiksi distopia. Ia lahir dari satu kata yang dulu kita kenal baik: bubble. Tahun 1930-an mengajarkan bahwa keserakahan sering menyamar sebagai optimisme. Hari ini, ia memakai nama baru: artificial intelligence.
Bubble AI membungkus ketidakpastian dengan janji masa depan. Valuasi melambung lebih cepat dari nalar. Modal mengalir bukan karena nilai, melainkan karena takut tertinggal. Ketika properti dulu runtuh, fondasi ekonomi Amerika ikut ambruk. Kini, jika AI kolaps, yang runtuh bukan hanya sektor—melainkan kepercayaan.
Pasar mencium bau itu. Dana melimpah, tetapi pinjaman sepi. Uang memilih diam. Ini bukan tanda sehat, melainkan insting bertahan hidup. Modal, seperti binatang liar, selalu lebih dulu tahu kapan gempa datang.
Cina melawan tanpa peluru. Supply chain menjadi senjata sunyi. Penyesuaian kecil, aturan administratif, keterlambatan teknis—cukup untuk membuat mesin industri Barat tersendat. Inflasi Amerika sulit jinak. Dolar mulai dipertanyakan. Dedolarisasi bukan sekadar kebijakan, melainkan imajinasi baru: dunia tanpa satu kitab suci mata uang.
Maka perhatian tertuju pada peristiwa yang tampak sepele: kunjungan Trump ke Beijing. Trump bukan ideolog. Ia pedagang. Cina tahu itu. Kadang, satu kompromi yang menyentuh kepentingan pribadi lebih ampuh daripada seribu pidato moral.
Dunia hampir terbakar bukan karena ideologi, melainkan kalkulasi untung-rugi. Dua gajah nyaris menanduk, tapi jeda sering ditentukan oleh bisikan, bukan teriakan.
Tahun 2026, dengan demikian, bukan soal menang atau kalah. Ia adalah ujian: apakah dunia runtuh oleh keserakahan yang dibungkus teknologi, atau diselamatkan oleh kompromi yang tak pernah disebut perdamaian. Sejarah, seperti biasa, tak memberi jawaban bersih. Ia hanya meninggalkan jejak—dan membiarkan kita menafsirkannya, sambil berdiri di atas tanah yang masih bergetar.